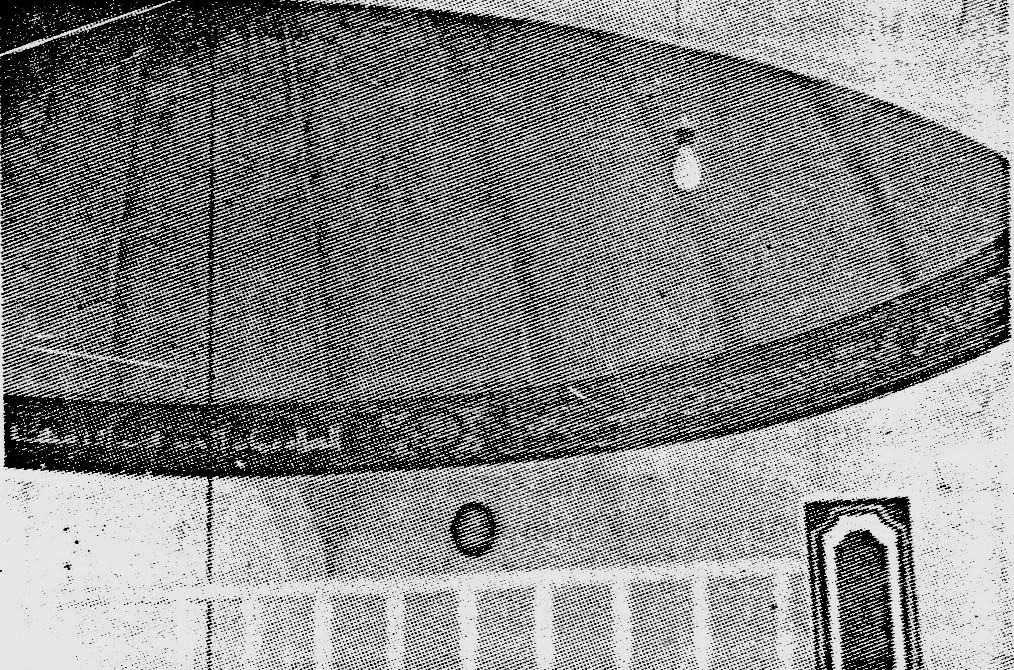BERHENTILAH membiasakan perendahan martabat terhadap jenis-jenis pekerjaan yang selama ini cenderung menjadi bahan olok-olok. Sesungguhnyalah Anda tidak pernah berhak mengatakan, ”Pantesan, anak tukang becak…”, ”Hanya kuli bangunan kok…”, ”Bali ndesa wae to, ben dadi cah ngarit”, ”Potongane kaya cah angon”, atau ”Tukang cuci kok macam-macam…”, ”Paling-paling ya jadi tukang parkir…”, atau ”Kerjanya hanya jaga masjid…”
Naluri stratifikasi sosialkah yang membentuk stigma sinis semacam itu? Ada latar perendahan kelas antara jenis pekerjaan yang ”profetik” dan yang dianggap sebagai ”liyan”. Maka yang liyan pun teropinikan harus berada di pinggir, hanya patut diolok-olok untuk meninggikan martabat yang ”priayi” atau ”berbaju bersih”, dan memosisikan yang belepotan kotoran, debu, atau harus siap diperintah oleh ”majikan” pada ruang yang lain.
Maka berhentilah membiasakan olok-olok itu, setidak-tidaknya ketika berkaca pada Suyatno, tukang becak di Yogyakarta yang Kamis lalu mendampingi wisuda dokter anaknya, Agung Bhaktiyar di Graha Sabha Pramana Universitas Gadjah Mada.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Simaklah keluarga pria 63 tahun ini. Saniyem, istrinya yang buta huruf, sehari-hari menjual rongsokan di pasar dibantu anak pertamanya. Anak keduanya menjadi tukang parkir, dan yang ketiga merantau ke Medan mengikuti suaminya. Agung membuat lompatan besar keluarga ini dengan menjadi seorang dokter.
Memosisikan istimewa momen ini, sejatinya adalah juga menciptakan ”penggolongan kelas”. Realitas tukang becak di satu pihak, dan kemewahan gelar dokter pada sisi yang lain. Bukankah korelasinya adalah stratifikasi kelas yang hidup di masyarakat itu sendiri? Seolah-olah hak atas profesi dokter hanya melekat pada mereka yang berduit, atau yang punya cukup akses pendidikan. Kuliah kedokteran juga identik dengan biaya tinggi, dari pendaftaran, proses belajar, praktikum, hingga fase co-ass.
Padahal, dengan kisah Agung Bhaktiyar, hak itu sesungguhnya melekat pada ”kesempatan”, dan kesempatan lahir dari kemampuan. Persoalannya, bagaimana kemampuan bisa terakses oleh otoritas yang punya kewenangan memutuskan sehingga mewujud menjadi ”kesempatan”?
* * *
KISAH ”dokter becak” Yogyakarta itu tentu bukan ”Cinderella” pertama dari sebuah proses pendidikan yang masih lebih banyak terukur dari biaya dan akses. Ada ”sarjana pertanian masjid”, ”sarjana hukum cengkih”, ”insinyur sengon”, ”sarjana komunikasi parkir”, dan sebagainya yang menggambarkan stereotipe ”proses perjuangan” untuk menopang biaya kuliah.
Perjalanan Agung Bhaktiyar setidak-tidaknya membuka pencerahan dua titik sikap. Pertama, masyarakat kita harus menjauhi olok-olok tentang stratifikasi sosial, karena sinisme tentang ”anak tukang becak”, ”anak petani”, ”anak kuli bangunan”, secara ekstrem bisa dihadapkan pada olok-olok yang sekarang ini rasanya bisa kita kembangkan, misalnya ”anak koruptor”, ”anak penyuap”, ”anak mafia hukum”, ”anak makelar kasus”, ”anak mafia pemilu”, dan semacamnya.
Kemuliaan pekerjaan apa pun, di wilayah ”baju bersih” atau ”priayi”, atau di lahan yang belepotan tanah lumpur atau pemulung, bukankah terletak pada kesungguhan, dedikasi, dan kejujurannya?
Titik sikap kedua, bagaimana keberpihakan dunia pendidikan kita kepada talenta-talenta yang tidak punya cukup dana. Akses itu memang sudah dibuka lewat berbagai program. Ada perguruan tinggi pemberi beasiswa bagi calon mahasiswa berprestasi olimpiade, bebas biaya kuliah bagi para hafidz Alquran, juara-juara olahraga, dan bentuk-bentuk yang lain.
Kemauan untuk tidak menjauhkan roh pendidikan dari idealita ”untuk semua”, atau bukan ”hanya untuk yang berduit” akan diuji lewat kemunculan bakat-bakat istimewa dari latar belakang keluarga yang minim akses, seperti proses anak Pak Suyatno itu di UGM. Inilah penegasan bahwa cah ngarit, cah angon, atau anak-anak buruh bangunan bukanlah liyan untuk tumbuh dan meraih hak yang setara dengan mereka yang punya segalanya…
Bukankah pemartabatan anak-anak bangsa lewat penyediaan ruang untuk bakat-bakat unggul di sebuah sekolah atau perguruan tinggi, hakikatnya hanya remah-remah, sudut kecil dari lahan lebih luas bagi mereka yang tidak punya masalah hidup untuk menuntaskan pendidikannya? (10)
Amir Machmud NS, wartawan Suara Merdeka
Sumber: Suara Merdeka, 12 September 2011