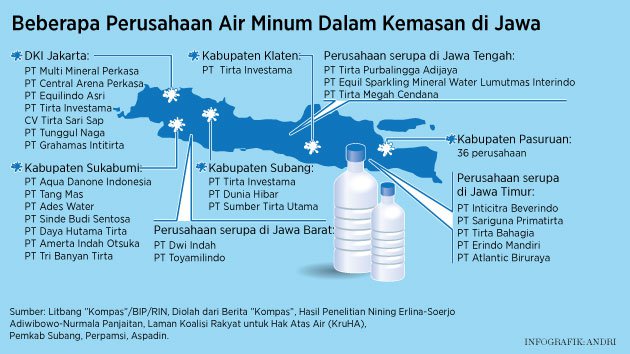Dua peristiwa bersejarah terkait air bersih terjadi tiga bulan terakhir. Pertama, Mahkamah Konstitusi membatalkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Rabu (18/2). Kedua, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan sebagian gugatan pembatalan kontrak swastanisasi pengelolaan air bersih di DKI Jakarta, Selasa (24/3).
”MK mungkin melihat UU ini terlalu liberal,” ujar Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan, Rakyat Basuki Hadimuljono, dalam jumpa pers merespons pembatalan UU Sumber Daya Air (26/2), ”Momentumnya sekarang adalah mengembalikan pengelolaan air kepada negara.”
Sebelum itu, permohonan uji materiil UU Sumber Daya Air sudah diajukan belasan organisasi non-pemerintah, sejak UU itu disahkan DPR, 19 Februari 2004. Namun, MK menolaknya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sementara itu, Selasa (24/3) malam, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan sebagian gugatan warga (citizen lawsuit) yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ).
Para tergugat adalah Presiden dan Wakil Presiden RI, Menteri Keuangan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Gubernur DKI Jakarta, DPRD DKI, PT Perusahaan Air Minum (PAM), PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja), serta PT Aetra Jaya (dulu PT Thames PAM Jaya).
Majelis hakim membatalkan kerja sama PAM Jaya dengan PT Palyja dan Aetra, yang dibuat 6 Juli 1997, diperbarui 28 Januari 1998 dan 22 Oktober 2001. Semua adendum dinyatakan tak berlaku lagi.
Puluhan sidang sudah digelar sejak gugatan dilayangkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tahun 2012. Masyarakat mengajukan 120 bukti tertulis bahwa kontrak swastanisasi melanggar konstitusi dan merugikan masyarakat. Ironisnya, kontrak berakhir tahun 2023.
Siaran pers KMMSAJ (16 Agustus 2011) menguraikan rata-rata konsumen harus membayar Rp 7.800 per meter kubik dengan tingkat kebocoran 45 persen. Di Surabaya, tarif per meter kubik Rp 2.600, tingkat kebocoran sekitar 30 persen.
Tingkat kebocoran 45 persen merupakan salah satu tertinggi di Asia jika mengacu pada laporan David Hall dan Emanuele Lobina dari Universitas Greenwich, London, ”Pipe Dreams: The Failure of the Private Sector to Invest in Water Services in Developing Countries” (2006).
Tarif rata-rata air bersih di DKI 0,7 dollar AS (kurs 2011), sedangkan di Singapura 0,35 dollar AS (kualitas siap minum), Filipina (0,35 dollar AS), Malaysia (0,22 dollar AS), dan Thailand (0,29 dollar AS).
Perlawanan
”Kemenangan” gugatan warga ini membuat Jakarta bergabung dengan perjuangan warga dari sedikitnya 100 kota di dunia—dari Bolivia ke Afrika Selatan, lalu ke Inggris Raya dan California, AS—sejak awal tahun 2000-an, untuk mengembalikan kontrol air bersih dan jaringan sanitasi kepada masyarakat dan pemerintah kota.
Gelombang privatisasi dimulai awal tahun 1990-an ketika korporasi multinasional memusatkan investasi di perkotaan di jazirah selatan global, dari Amerika Selatan ke Asia Timur.
Privatisasi air, didukung lembaga-lembaga keuangan multilateral, seperti Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional, diyakini memperluas akses air bersih kepada tiga miliar orang di dunia. Protes meruyak karena agendanya kian terungkap: air sebagai komoditas.
Penggunaan dan distribusinya ditentukan prinsip keuntungan, bukan keadilan dan keterjangkauan, atas nama hak rakyat atas air bersih. Dengan mengungkapkan pengalaman di berbagai negara, hal itu dikemukakan Emanuele Lobina yang dihadirkan sebagai saksi ahli dalam salah satu sidang di Jakarta.
Dengan privatisasi, diyakini, kebutuhan air satu miliar orang di Afrika sub-Sahara, Asia Selatan, dan Asia Timur (tak termasuk Tiongkok) terpenuhi dalam sembilan tahun (2006-2015).
Kawasan itu juga diprediksi mencapai target Tujuan Pembangunan Milenium (MDG), yaitu berkurangnya separuh jumlah orang tanpa akses terhadap air bersih dan sanitasi dasar (270.000 orang per hari). Namun, penelitian Hall dan Lobina (2006), dalam sembilan tahun itu, sektor swasta hanya mampu menjangkau rata-rata 900 orang per hari.
Dalam Blue Gold: The Battle Against Corporate Theft of the World’s Water (2002), Maude Barlow dan Tony Clarke memaparkan, perlawanan legendaris terhadap korporasi air dan pemerintah yang menandatangani perjanjian terjadi tahun 2000 di kota Cochabamba, Bolivia. Gugatan investor asing diselesaikan melalui kesepakatan, awal 2006.
Pada tahun sama, warga Grenoble, Perancis—markas korporasi air dunia—merayakan kembalinya kontrol air bersih dan air kotor ke tangan publik setelah berjuang lebih satu dekade. Pada tahun 2006, mantan wali kotanya dijatuhi hukuman karena skandal suap terkait itu.
Di AS, kelompok masyarakat, pekerja layanan publik, dan anggota dewan kota bekerja sama melawan privatisasi air di Illinois, Alabama, dan California. Perlawanan juga terjadi di seluruh Kanada.
Belum utuh
Dikabulkannya sebagian gugatan itu, menurut Arif Maulana dari LBH Jakarta, belum merupakan kemenangan utuh. Itu karena majelis hakim tidak menolak permintaan banding pihak tergugat atas putusan sidang.
”Memang, ada legitimasi kuat dengan keputusan kemarin,” ujarnya, ”Tinggal keberanian pemimpin mengambil risiko dan bersuara lantang tentang kedaulatan.”
Menurut Arif, target advokasi bukan kemenangan pengadilan, melainkan kesadaran publik bahwa air bersih adalah hak dasar setiap warga negara serta bagaimana negara mengambil peran untuk memastikan pengelolaan yang menghasilkan pelayanan publik berkualitas, sesuai prinsip hak rakyat atas air sesuai dengan konstitusi dan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya.
Pengamat sumber daya air, Nila Ardhianie, menambahkan, ”Mudah-mudahan Gubernur DKI akan menjadi pemimpin pertama yang melaksanakan amanat konstitusi dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan merealisasikan pengurusan dan pengelolaan air oleh pemerintah.”
Arif mengingatkan model baru dalam pengelolaan air, seperti disyaratkan Emanuele Lobina, yang mengandung nilai-nilai solidaritas, kolaborasi, efektivitas sosial, kepercayaan, dan keterbukaan. Semua itu hanya bisa diwujudkan jika warga, komunitas, operator publik, dan pekerja bekerja bersama-sama. MARIA HARTININGSIH dan GESIT ARIYANTO
———————–
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 31 Maret 2015, di halaman 14 dengan judul “Mematahkan Mitos Privatisasi”.