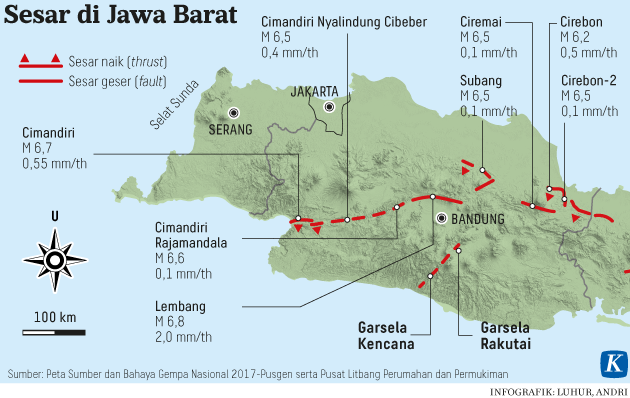Fenomena psikologi yang dikenal sebagai Stockholm Syndrome, seperti diamati para pakar psikologi sosial, merupakan salah satu paradoks kasus-kasus kekerasan.
Sindrom yang didefinisikan psikiater Frank Ochberg itu merupakan fenomena psikologi di mana korban menunjukkan kepedulian, simpati, empati, dan perasaan positif pada pelaku. Tindak kekerasan dipahami secara salah sebagai kebaikan.
Majalah Time (31/8/2009) memuat kasus Jaycee Lee Dugard yang diculik ayah tirinya pada 1991 dalam usia 11 tahun. Ia tak mencoba lolos dan bahkan mencintai ayah tirinya yang terus-menerus memerkosanya. Di Indonesia banyak kasus serupa. Di antaranya, kasus Lara (sebut saja begitu), yang dijual ayah kandungnya sejak usia 13 tahun. Namun, saat dilamar sang ayah, ia menyatakan ’ya’, asal ibunya diceraikan (Kompas, 8/2/2013).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Istilah ”Stockholm Syndrome” yang digulirkan kriminolog dan psikiater Swedia, Nils Bejerot, terkait peristiwa perampokan Kreditbanken di Norrmalmstorg, Stockholm, Swedia, diikuti penyanderaan empat pegawainya, 23-28 Agustus 1973. Penyekapan itu melahirkan semacam ikatan emosional antara korban dan pelaku, membuat korban menolak bantuan aparat. Setelah bebas, korban malah membela para penyekapnya.
Stockholm Syndrome terlihat jelas pada kasus Patty Hearst, putri jutawan penerbit AS, Randolph Hearst. Ia diculik kelompok Symbionese Liberation Army (SLA) pada usia 19 tahun pada 1974. Namun, bersama SLA, ia kemudian ikut merampok bank.
Stockholm Syndrome atau capture-bonding, menurut psikolog Donald G Dutton dan Susan Painter dalam ”Emotional Attachment in Abusive Relationship: A Test of Traumatic Bonding Theory” dalam Jurnal Violence and Victims Vol 8 No 2 (1993), merupakan bentuk ikatan trauma atau ikatan teror, yang tak selalu mengikuti skenario penyanderaan. Ia bisa dijabarkan sebagai ”ikatan emosional” yang kuat antara dua pihak, di mana satu pihak terus melakukan perundungan, pemukulan, ancaman, dan intimidasi terhadap pihak lain. Hal ini bisa dilihat, antara lain, juga pada kasus-kasus paedofilia.
Meyakini nilai sama
Salah satu hipotesis untuk menjelaskan efek Stockholm Syndrome berbasis teori Freud menyatakan, ikatan itu sebagai tanggapan individual terhadap trauma dalam proses menjadi korban. Begitulah cara ego mempertahankan diri. Ketika korban meyakini nilai-nilai pelaku, mereka bukan lagi ancaman.
Meski demikian, hampir semua teori tak bisa menjelaskan sindrom itu secara komprehensif. Termasuk teori Dee LR Graham dalam Loving to Survive: Sexual Terror, Men’s Violence, and Women’s Lives (1994) yang menengarai lumpuhnya akal sehat masyarakat oleh sindrom tersebut. Ia menuding kuatnya kultur patriarki sebagai penyebabnya.
Selain kasus-kasus kekerasan di ruang privat, mekanisme capture-bonding tampak jelas dalam pelatihan dasar militer, ikatan kelompok lewat perploncoan (kasus-kasus STPDN dan lain-lain), dan perilaku sadisme atau masoschism. Para antropolog menunjuk suku Yanomamo di Amerika Selatan, yang anggotanya adalah keturunan tiga generasi suku-suku lain yang disandera.
Para ahli teori ekonomi menggunakan konsep Stockholm Syndrome mengacu pada pemerintah yang ”disandera” modal finansial karena kebutuhan merestrukturisasi utang. Mereka menukar kedaulatan negara dengan menerima prasyarat dan utang berbunga tinggi dari lembaga-lembaga pemberi utang.
Saatnya ahli teori politik memperkenalkan konsep yang sama pada situasi di mana korban kekerasan politik berbalik mendukung, bahkan ”mencintai” para pelaku….
Oleh: Maria Hartiningsih
Sumber: Kompas, 14 Mei 2014