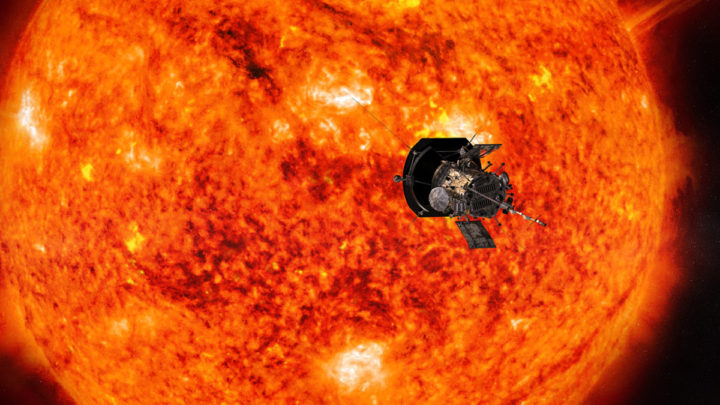Media massa berada pada posisi antara, berdiri antara kepentingan publik dan kepentingannya. Peliputan bencana ujian paling nyata. Media akan dihadapkan pada tuntutan memberikan informasi mencerahkan yang mendorong pengurangan risiko bencana atau memilih melaporkan sebagai komoditas belaka dengan aspek utama dramatisasi tragedi.
Di Indonesia, tren peliputan bencana cenderung mengejar sisi dramatis. Peliputan bencana identik dengan darah, mayat, dan air mata, sebagaimana ditampilkan dalam peliputan tsunami Aceh 2004 hingga jatuhnya pesawat AirAsia QZ8501 pada 2015 atau sederet kejadian bencana lainnya.
Pertanyaan-pertanyaan reporter saat peliputan jatuhnya pesawat bertendensi memainkan emosi keluarga korban yang dilanda kecemasan. Begitu mayat korban ditemukan, ada televisi yang memajang gambarnya secara vulgar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Potret buruk media yang mengumbar mayat korban jatuhnya AirAsia mengundang kecaman media internasional, seperti ditulis Times (30/1/2015), “AirAsia Relatives in Shock as Indonesian TV Airs Images of Floating Body.”
Masalahnya, dramatisasi tayangan itu dilakukan sadar, seperti disampaikan produser televisi swasta di Jakarta, “Kami butuh gambar dan suasana yang dramatis untuk menarik pemirsa. Masyarakat Indonesia itu menyukai kisah-kisah melodrama. Bagi kami, rating adalah segalanya. Lagi pula, ini dibutuhkan untuk menarik empati bagi masyarakat untuk menyumbang korban bencana.”
Dalam perspektif ekonomi politik, konstruksi berita di media massa jelas tidak bisa dilepaskan dari kepentingan bisnis. Rating dalam media televisi atau hits bagi media daring dan tingkat keterbacaan bagi media cetak menjadi panglima dalam liputan media. Itulah kontradiksi media karena publik juga menuntut adanya tanggung jawab sosial dari media.
 KOMPAS/AHMAD ARIF–Pengunjung pada Disaster Reduction and Human Renovation Institution di Kobe, Jepang, memperhatikan barang-barang milik penyintas dan pesan-pesan yang mereka tulis terkait gempa yang melanda kota itu 21 tahun silam, Minggu (28/2). Selain pendidikan kebencanaan di sekolah ataupun museum-museum, peran media yang terus mengingatkan tentang mitigasi bencana juga menjadi kunci penting kesuksesan Jepang membudayakan kesiapsiagaan menghadapi bencana.
KOMPAS/AHMAD ARIF–Pengunjung pada Disaster Reduction and Human Renovation Institution di Kobe, Jepang, memperhatikan barang-barang milik penyintas dan pesan-pesan yang mereka tulis terkait gempa yang melanda kota itu 21 tahun silam, Minggu (28/2). Selain pendidikan kebencanaan di sekolah ataupun museum-museum, peran media yang terus mengingatkan tentang mitigasi bencana juga menjadi kunci penting kesuksesan Jepang membudayakan kesiapsiagaan menghadapi bencana.
Praktik peliputan bencana yang lebih menekankan aspek dramatisasi tragedi itu memang tidak khas dilakukan media di Indonesia. “Tidak ada media di Turki yang fokus pada liputan tentang mitigasi bencana. Mereka meliput bencana setelah kejadian,” kata Gulum Tanircan, Koordinator Disaster Preparedness Training Unit KOERI (Kandili Observatory and Earthquake Research Institute) Turki, dalam lokakarya dan simposium tentang media dan bencana, yang digelar di Pusat Riset Mitigasi Bencana, Nagoya University, Jepang, akhir Februari lalu. Acara tersebut fokus pada kolaborasi media dan lembaga riset dalam menyebarkan informasi kebencanaan dan dihadiri perwakilan ilmuwan serta jurnalis dari Cile, Turki, Jepang, dan Indonesia.
Fenomena sama disampaikan Soledad Puente, peneliti pada Pontificia Universidad Catolica de Chile. Menurut Puente, media massa di Cile cenderung fokus memberitakan tragedi setelah kejadian dengan pendekatan drama. Dalam istilah sosiolog media John H Macmanus (Market Driven Journalism, 1994), media mengekspos berbagai bentuk peristiwa bencana alam, seperti gempa dan banjir, secara sadar dan sistematis mengikuti logika komersial semata.
Dalam simposium, Kepala Seksi Advokasi dan Hubungan Luar United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNISDR) Jerry Velasquez menyatakan, “Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030 telah mengamanatkan agar semua negara fokus pada pengurangan korban dan dampak bencana dibandingkan dengan penanganan pasca bencana.”
Terkait itu, menurut Velasquez, industri media dituntut mengubah perspektif dalam meliput bencana. Mereka harus meninggalkan model peliputan yang hanya mengutamakan kepentingan peringkat ataupun peningkatan oplah. Media juga dituntut mengedepankan tanggung jawab kemanusiaan.
Salah satu model yang dijadikan contoh adalah praktik para pelaku media di Nagoya, Jepang, dengan membentuk Networking for Saving Lifes (NSL). Forum itu dinilai terobosan baru dalam rangka membangun kesadaran bersama di kalangan jurnalis di Nagoya agar lebih berperan dalam pengurangan risiko bencana di kotanya.
Pelajaran dari Nagoya
Sebagaimana disampaikan Kunihiko Kumamoto, Guru Besar Komunikasi Media Universitas Edogawa, sejak 2001, para jurnalis di Nagoya mengesampingkan persaingan demi membangun NSL. Jaringan itu kumpulan wartawan sejumlah media massa di Nagoya yang rutin bertemu setiap bulan dengan para akademisi, peneliti, dan pemerintah daerah untuk membahas kesiapsiagaan kota mereka menghadapi bencana, terutama ancaman gempa dan tsunami.
Pada forum itu, para partisipan saling bicara terbuka tentang kelemahan sistem dan hal yang harus dibenahi. Disepakati, pertemuan itu tidak untuk dilaporkan, tetapi saling mempertajam perspektif dan kepekaan terhadap kotanya. “Selain menambah pengetahuan baru, terutama bagi jurnalis, hal itu juga untuk membangun kepercayaan antarpihak, terutama wartawan dan ilmuwan, yang cenderung berjarak,” kata Kumamoto, mantan wartawan NHK.
Nobuhiro Igarashi dari Nagoya Broadcasting Network menambahkan, NSL membantu wartawan lebih paham soal kebencanaan karena bisa berdiskusi dengan para ilmuwan. Hal lebih penting, itu membantu meningkatkan tanggung jawab dan semangat para wartawan untuk turut mengurangi risiko bencana di kotanya.
Praktik peliputan bencana secara konstruktif itu tidak hanya dipraktikkan di Nagoya. Berbeda dengan kebanyakan media lain, termasuk Indonesia, media di Jepang tak menampilkan gambar mayat korban bencana. Bahkan, orang menangis.
Pada liputan tsunami Tohoku 2011, tak satu pun media Jepang (baik televisi, cetak, maupun daring) menampilkan gambar mayat korban. Gambar-gambar orang menangis pun susah ditemui. Bahkan, iklan layanan komersial pun menghilang dari televisi, digantikan iklan layanan masyarakat, seperti ajakan menghormati orangtua dan membantu orang lain.
Perbedaan media Indonesia dan Jepang dalam meliput bencana itu dikisahkan mantan wartawan senior koran Yomiuri Shimbun, Yoshinari Kurose, yang pernah bertugas di Indonesia 2002-2006. Ia juga meliput tsunami Aceh 2004. “Saya terkejut, gambar-gambar mayat mendominasi media di Indonesia. Di Jepang, media tidak bisa menampilkan cerita sedih yang bisa memicu trauma. Bagaimana penanganan korban, bagaimana hidup mereka selanjutnya. Itu lebih penting diberitakan.”
Kecenderungan media di Jepang yang membingkai bencana lebih “konstruktif” itu memang bukan tanpa cela. Banyak kritik ditujukan kepada media-media di Jepang yang dinilai tak memberikan gambaran nyata kebocoran radiasi nuklir PLTN Fukushima, yang terpicu tsunami 2011. Kritik juga mengarah pada kecenderungan media di Jepang yang relatif seragam dan minim kritik pada kebijakan pemerintah dalam penanganan bencana.
Beberapa penelitian menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat Jepang terhadap media mereka menurun setelah tsunami 2011. Sebagian mencari info di internet dan media asing yang dianggap memberikan informasi lebih lengkap tentang ancaman radiasi Fukushima.
Belajar dari Jepang dan melihat realitas komodifikasi berita bencana di Indonesia, yang bisa dilakukan untuk memperbaiki mutu liputan di Indonesia adalah memperbaiki prosedur operasi standar meliput bencana, menegakkan kode etik, dan paling penting membangun kesadaran: meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana adalah tanggung jawab bersama.–AHMAD ARIF
————————–
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 8 April 2016, di halaman 14 dengan judul “Berjejaring Selamatkan Hidup”.