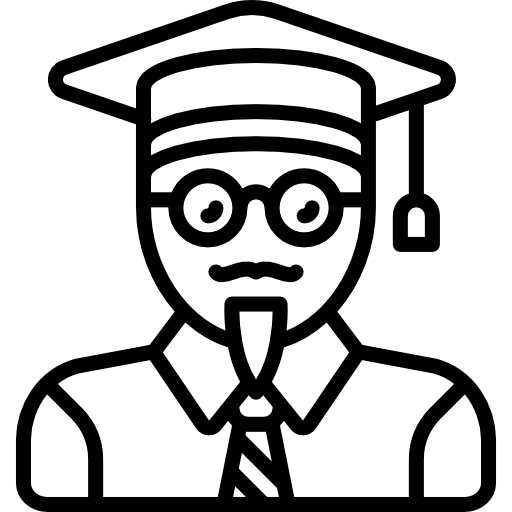Presiden Susilo Bambang Yudhoyono baru saja memperoleh gelar profesor bidang Ilmu Ketahanan Nasional dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Sebelumnya mantan Kepala BIN AM Hendropriyono menerima gelar serupa dalam Ilmu Intelijen.
Kemudian muncul pertanyaan, mengapa keduanya bisa memperoleh gelar profesor, padahal mereka bukan dosen di perguruan tinggi? Bukankah pencalonan mereka tidak melalui pemeriksaan berkas yang superketat dari Dikti seperti yang dialami para calon guru besar di perguruan tinggi?
Akan tetapi, pertanyaan seperti itu menjadi tidak relevan lagi sekarang ini karena jabatan profesor dapat disematkan kepada pengemban profesi apa pun, termasuk perwira militer, politikus, atau pejabat negara. Dasar hukumnya UU No 12/2012 dan Permendiknas No 88/2013. Kedua peraturan itu diterbitkan pada era pemerintahan SBY.
Jika dicermati isi kedua peraturan tersebut, secara implisit Mendikbud dapat mengangkat guru besar yang bersifat kehormatan karena untuk mendapatkan gelar ini, calon tidak perlu berstatus sebagai dosen tetap dan telah melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi dan kepadanya tidak diberikan tunjangan jabatan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pemberian gelar guru besar ini tampaknya dapat disejajarkan dengan pemberian gelar doktor honoris causa oleh universitas kepada tokoh yang mempunyai prestasi luar biasa dalam bidang tertentu.
Landasan hukum yang digunakan untuk memberikan gelar tersebut adalah ketentuan dalam UU No 12/2012 Pasal 72 (5) yang berbunyi: ”Menteri dapat mengangkat seseorang dengan kompetensi luar biasa pada jenjang jabatan akademik profesor atas usul perguruan tinggi”.
Istilah ”kompetensi luar biasa” itu dijelaskan dalam Permendikbud No 88/2013 Pasal 2 (2) yang berbunyi: ”yang bersangkutan memiliki karya yang bersifat pengetahuan tacit yang memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi pengetahuan eksplisit di perguruan tinggi dan bermanfaat untuk kesejahteraan umat manusia”.
Bukti yang dipakai Kemdikbud untuk menunjukkan bahwa penerima gelar tersebut memenuhi kriteria yang dimaksud adalah bahwa penerima gelar itu sudah berhasil mendirikan pendidikan tinggi dalam ilmu baru yang belum pernah diajarkan di tempat lain. Hendropriyono mendirikan Sekolah Tinggi Intelijen Negara, sementara SBY mendirikan Universitas Pertahanan Nasional.
”Tacit” ke eksplisit
Agar dapat diketahui ketepatan pemberian gelar tersebut, perlu terlebih dahulu dikaji apakah itu ”pengetahuan tacit”. Kapan pengetahuan tacit bertransformasi menjadi pengetahuan eksplisit? Apakah pendirian pendidikan tinggi oleh dua penerima gelar profesor tersebut telah memadai sebagai bukti keberhasilan keduanya melakukan transformasi pengetahuan dari tacit ke eksplisit?
Pengetahuan tacit adalah pengetahuan yang tidak tertulis, tidak terucapkan atau tersembunyi yang dimiliki orang berdasarkan pada emosi, pengalaman, imajinasi, intuisi, observasi, dan akumulasi informasi. Sementara itu, pengetahuan eksplisit adalah pengetahuan yang bersifat formal dan sistematis. Pengetahuan seperti ini mudah dikomunikasikan dan dibagikan kepada orang lain.
Di dunia ilmu contoh nyata dari kapasitas melakukan transformasi pengetahuan seperti itu ada pada Bapak Ilmu Manajemen Frederick Winslow Taylor, seorang insinyur dan manajer perusahaan di Amerika Serikat pada awal abad ke-20, yang mampu mempelajari cara-cara organisasi beroperasi atau cara-cara perusahaan melakukan proses produksi secara ilmiah sehingga melahirkan teori yang disebut scientific management.
Sebelum Taylor, proses produksi di pabrik sangat bergantung kepada penguasaan rule of thumb, atau pengetahuan tacit dari para pekerjanya. Pengetahuan tersebut diperoleh oleh buruh secara personal berdasarkan pengalaman masing-masing sekian tahun magang di perusahaan.
Namun, Taylor mampu meneliti secara ilmiah cara bekerja seperti itu dan melahirkan teori-teori manajemen seperti teori Ban Berjalan, one best method, dan Time and Motion yang dapat dipelajari dan dipraktikkan oleh semua pekerja di perusahaan sehingga terjadi efisiensi produksi. Teori Taylor ini banyak memengaruhi para sarjana dan praktikus manajemen dan Taylorisme menjadi satu paradigma tersendiri dalam sejarah ilmu administrasi atau manajemen.
Apakah kedua penerima gelar profesor tersebut di atas mempunyai kualifikasi seperti tokoh yang dicontohkan tadi? Jawaban pertanyaan ini dapat dicari dari salah satu alasan mengapa mereka mendapatkan gelar tersebut.
Tidak ada hubungan
Hendropriyono berjasa mendirikan Sekolah Tinggi Intelijen Negara. Sementara itu, SBY berjasa telah mendirikan Universitas Pertahanan Nasional. Keduanya dianggap sebagai ilmu baru. Mendirikan lembaga pendidikan tinggi baru tidak secara otomatis dapat disebut melakukan transformasi pengetahuan dari tacit ke eksplisit meskipun bidang ilmu yang diajarkan di sekolah tersebut dipandang baru. Apalagi jika semua pengetahuan yang diajarkan di sekolah tersebut merupakan pengetahuan eksplisit yang telah lama tersedia di literatur, bukan pengetahuan eksplisit yang secara orisinal dihasilkan oleh yang bersangkutan dan diakui oleh komunitas ilmuwan di bidangnya sebagai baru dan berpengaruh.
Bukti karya transformasi akan tampak jika dapat ditelusuri karya ilmiah yang bersangkutan. Paling mudah, karya ilmiah yang dimaksud dapat ditelusuri dari tema disertasi para penerima gelar tersebut.
Hendropriyono menyusun disertasi untuk sekolah S-3-nya di Fakultas Filsafat UGM berjudul ”Terorisme dalam Kajian Filsafat Analitika”. Disertasi ini seluruhnya menganalisis pengetahuan eksplisit yang telah lama ada, bukan mentransformasi pengetahuan tacit. Judul ini pun berbeda dengan bidang ilmu yang dilekatkan untuk gelar guru besarnya, yaitu Ilmu Intelijen.
Judul disertasi SBY dalam studi S-3-nya di IPB adalah ”Pembangunan Pertanian dan Perdesaan sebagai Upaya Mengatasi Kemiskinan dan Pengangguran: Analisis Ekonomi Politik Kebijakan Fiskal”. Disertasi ini juga membahas pengetahuan eksplisit yang telah lama ada. Kajian ini pun juga tidak ada hubungannya dengan bidang ilmu dari gelar guru besar yang diberikan, yaitu Ilmu Pertahanan Nasional.
Muhadjir Darwin, Guru Besar Manajemen dan Kebijakan Publik Fisipol UGM dan Peneliti pada Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM
Sumber: Kompas, 17 Juli 2014