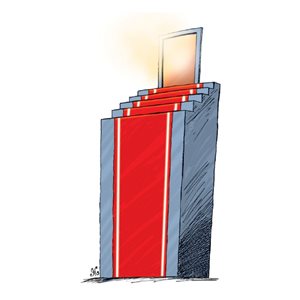Lebih dari dua tahun lalu saya menulis “Rumitnya Jenjang Karier Dosen” (Kompas, 16/2/2013). Kali ini saya menulis demikian rumitnya jenjang karier dosen oleh tambahan peraturan dari pemerintah.
Peraturan itu ironis dengan fakta bahwa penyelenggara pendidikan tinggi terus mengeluhkan betapa sulit merekrut dosen. Karier dosen bukan pilihan terbaik lulusan S-1 hingga S-3 kita, apalagi jika mereka tahu jenjang karier dosen amat rumit.
Saya mengikuti beberapa pertemuan terkait sumber daya dosen di tingkat nasional. Pertemuan terakhir bersangkutan secara khusus dengan dosen Fakultas Kedokteran. Sungguh sulit merekrut dokter jadi dosen, apalagi, setelah direkrut, lebih sulit lagi membina dan mempertahankan dosen. Mengapa jenjang jabatan akademik dosen perlu diperumit lagi? Tulisan Rhenald Kasali (Kompas, 15/9/2014) yang disanggah Erry Yulian Triblas Adesta (Kompas, 2/12/2014) menunjukkan kegelisahan apa benar “harga dosen naik?”.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Tulisan ini menyumbang saran bagaimana mungkin menaikkan harga dosen jika penilaian atas kualitas dosen demikian kaku dari pemerintah, yang mengatur jenjang karier dosen? Apakah perguruan tinggi negeri (PTN) dan perguruan tinggi swasta (PTS) akan memperebutkan dosen yang “hanya” asisten ahli? Berapakah “harga dosen” lektor kepala, sementara karena kakunya peraturan, lektor kepala saat ini harus doktor? Cukup berhargakah dosen muda yang belum S-2/S-3 dan hanya menunjukkan potensi publikasi?
Segera pula teringat isu tentang otonomi perguruan tinggi sebagaimana terus didengungkan Satryo Soemantri Brodjonegoro (terakhir: Kompas, 9/3/2015), termasuk tulisan para pakar pendidikan tinggi yang pro otonomi pendidikan tinggi dalam beragam aspek. Benarkah langkah pemerintah jadi penentu hingga juklak perhitungan teknis dan aturan kaku menilai karier dosen sehingga dosen di mana pun berada dengan sifat institusi sangat heterogen dinilai dengan cara seragam? Demikian besarkah kekuatan aturan pemerintah menentukan jenjang karier dosen secara sama rata?
Perhitungan teknis
Awal November 2014 ada perubahan pada perhitungan teknis beban kredit untuk publikasi ilmiah internasional dengan perhitungan kredit demikian kaku. Sebelumnya, publikasi internasional dapat memiliki poin maksimal 40, kini dibuat tiga kategori: maksimal 40 poin, maksimal 30 poin, dan maksimal 20 poin. Kelas pertama untuk artikel yang terbit dalam jurnal ilmiah internasional dengan impact factor dan terindeks Scopus atau ISI; kelas kedua untuk yang tak memiliki impact factor, tetapi terindeks di Scopus atau ISI; kelas ketiga untuk yang terindeks “hanya” di Directory of Open Access Journal (DOAJ), Google Scholar, dan Copernicus.
Dalam kerumitan ini terkandung sedikitnya empat kekurangpahaman. Benarkah dosen kita mayoritas telah mampu atau dimampukan meneliti dan publikasi? Cukup dipahamikah makna terindeks oleh lembaga berbayar indeks? Dengan begitu rumitnya jenjang karier ini, bagaimana dunia pendidikan tinggi melakukan rekrutmen (naikkah harga dosen?)? Jika remunerasi bagi dosen masih dipandang tak menarik, apalagi dengan kerumitan jenjang karier, apakah yang dapat dijanjikan dunia pendidikan tinggi merekrut dosen baru (apalagi calon dosen berkualitas)?
Bahwa harga dosen naik dan jadi rebutan tentu akan benar bagi dosen berkualitas dan memenuhi tri dharma dengan mumpuni. Berapa persen yang demikian? Sementara, lembaga yang membesarkan dosen itu hingga mumpuni dapat ditinggalkan dan sah saja dalam dunia profesional. Pertanyaannya, bagaimana PT baru, PTS, PTN relatif berukuran sedang dan kecil dapat bersaing atau dapat mempertahankan para dosennya?
Tulisan ini hanya membahas masalah pertama. Perlu diakui, dosen di negeri ini amat heterogen. Ribuan alasan jadi dosen. Heterogenitas bukan saja personal, juga institusional. Jenjang PT terbagi secara institusional berdasarkan kepemilikan (PTN dan PTS) serta jenjang studi yang ditawarkan (D-1 hingga S-3). Heterogenitas termasuk juga penghargaan atas tersebarnya PTN dan PTS dari Sabang hingga Merauke. Lokasi menentukan warna karier dosen.
Keheterogenan juga berimbas pada karya ilmiah yang paling mungkin dihasilkan dosen pada keadaan tertentu. Jumlah publikasi berbanding positif dengan ragam prodi dan jenjangnya. Riset mengenai ini sudah banyak dilakukan para ahli manajemen pendidikan tinggi di dunia. Dapat ditengarai, PT berprodi S-2 dan S-3, para dosennya “diuntungkan” dengan ketersediaan sumber daya yang dapat bekerja sama untuk penelitian dan penulisan ilmiah demi kepentingan mutualisme akademik.
PT dengan prodi S-1 tentu masih dapat bekerja sama dengan produk penulisan ilmiah yang dapat saja terserap sebagai tulisan di jurnal internasional, tetapi dengan kemungkinan lebih kecil dibandingkan PT jenis pertama. Bagaimana dengan PT yang jenjang prodinya D-1 hingga D-3? Bagaimana dengan PT yang terletak di kepulauan dengan akses terbatas untuk publikasi ilmiah?
Sulit diseragamkan
Jelaslah, jenjang karier dosen atas nama heterogenitas amat sulit diseragamkan. Idiom “sejarah ditulis pemenang” agaknya menemukan pembenarannya pada aturan seragam jenjang karier dosen ini. Pemenangnya adalah institusi dengan umur cukup senior, memiliki sumber dana cukup untuk mayoritas dosennya melakukan penelitian dan publikasi, memiliki jenjang prodi sedikitnya S-1 dan terutama S-2 dan S-3, memiliki berbagai fakultas: ilmu sosial, IPA, terapan, serta studi komprehensif, memiliki pusat studi, jejaring nasional dan internasional.
Tak terlalu sulit memahami kebalikan dari semua sifat itu adalah ketakberdayaan dosen berkarier lebih cepat dan berkualitas, apalagi dengan peraturan sedemikian kaku dari pemerintah. Imbasnya, institusi yang tak memiliki sifat itu, atau mayoritas dari sifat tersebut, ditengarai tersendat. Apa yang harus dilakukan? Tentu telah ada upaya pemerintah mengangkat PT yang butuh asuhan. Bimbingan disediakan dalam rupa pertukaran dosen atau pakar dari PT lebih maju ke PT perlu bimbingan. Rekrutmen dosen PTN di beberapa tempat juga diberikan kuota lebih daripada di tempat yang sudah maju. Kopertis disediakan untuk membina PTS.
Langkah itu perlu dihargai. Meski demikian, jika aturan dibuat sangat kaku dan seragam (termasuk untuk pihak tak berdaya), memberdayakan yang kurang berdaya saja tak cukup. Asuhan perlu diberikan dalam kerangka kebijakan. Bantuan adalah kebijakan yang berbeda pada tenggat tertentu. Namun, jika hal ini dibuat, betapa banyak peraturan harus dimunculkan pemerintah karena heterogenitas tadi. Alternatif solusinya: beri ruang-waktu bagi PT yang perlu dibina dengan peraturan yang dibuat PT itu dengan pendampingan pemerintah.
Alternatif lain, pemerintah menghapus kekakuan peraturan baru itu. Sebagai imbal bagi prestasi dosen yang bisa melebihi aturan, beri penghargaan untuk dosen dan institusi yang memenuhi kriteria terbaik. Dengan alternatif ini, pemerintah dapat memfokuskan peraturan yang membela banyak khalayak civitas academica Indonesia (yang heterogen), sekaligus memfokuskan usaha memberdayakan institusi dan dosen yang perlu pembinaan. Tentu tak luput memberi pacuan kepada institusi dan dosen yang sudah terbina, sudah maju, untuk lebih maju. Peran ini lebih sederhana. Jelas lebih memberikan otonomi ke penyelenggara PT, tetapi juga memberi kesempatan pemerintah menjalankan fungsi monev.
Dalam pertemuan rapat koordinasi PTS, Direktur Direktorat Kelembagaan dan Kerjasama Ditjen Dikti Hermawan Kresno Dipojono mengandaikan tekad untuk orientasi pada riset 2045 dapat tercapai jika tahun ini tekad itu jadi histeria massa ristek, terutama para pihak terkait civitas academica pendidikan tinggi. Sudah saatnya pemerintah ambil peran lebih bijak, bukan pada produk kaku yang menghambat kemajuan pihak tak berdaya. Pemerintah adalah pembela dan pemberdaya bangsa Indonesia, termasuk civitas academica perguruan tinggi.
Elisabeth RukminiPengajar di Unika Atma Jaya, Jakarta
———————
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 29 April 2015, di halaman 7 dengan judul “Jenjang Karier Dosen”.