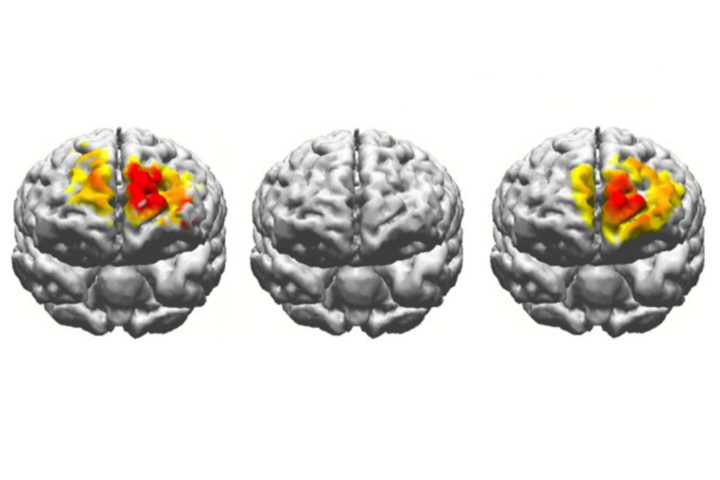Tes mental dirasakan banyak orang sebagai satu alat tambahan diskriminasi ras. Banyak yang menentang penerapan tes itu.
Di zaman modern ini, bila anda pernah duduk di SMA, biasanya anda pernah mengikuti tes inteligensi. Apakah tes inteligensi itu? Tes inteligensi, menurut Watren’s Dictionaru of Psychology , adalah “suatu soal atau serangkaian soal yang dihadapkan kepada seseorang untuk dipecahkan, atau suatu tugas atau serangkaian tugas yang harus dilakukan, dengan maksud untuk menentukan tingkat kemampuan mental yang bersangkutan.”
Cukup jelas, bukan? Sederhana sekali . Namun, nyatanya, tes inteligensi (tes IQ) erat dikaitkan dengan pendapat bahwa kepintaran alias inteligensi itu suatu sifat yang diturunkan. Sehingga banyak psikolog lebih suka tidak mempergunakan istilah tersebut . Dewan Riset Nasional AS melaporkan, tahun 1982, bahwa kenyataan itu sungguh tidak menguntungkan. Ia bisa menimbulkan salah faham, karena inteligensi dapat diartikan sebagai suatu kemampuan yang menyatu, tertentu jumlahnya, tidak berubah selamanya, dan karenanya seseorang dapat digolong-golongkan dengan sekali tes IQ. Padahal, kenyataannya, tidak demikian.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
 —Alfred Binet, bapak tes IQ
—Alfred Binet, bapak tes IQ
Konsep inteligensi sebagai kemampuan mental umum sudah ada sejak zaman Aristoteles. Sedangkan ide bahwa inteligensi merupakan keturunan dicetuskan oleh Francis Galton, saudara sepupu Charles Darwin, yang dalam tahun 1869 mengadakan pengamatan bahwa “orang besar” di Inggris masanya mengikuti garis keturunan keluarga. Kesimpulan Galton, “Orang Besar”, menyediakan inti keturunan, asal kemampuan yang lama kelamaan luntur karena semakin menipisnya darah asal itu pada keturunan belakangan.
Galton jugalah yang mencetuskan ide bahwa inteligensi dapat diukur dengan suatu tes. Ia menduga, bahwa pengetahuan masuk ke dalam otak melalui panca indera. Maka dikembangkanlah teori inteligensi dengan jalan mengukur kepekaan mata dan telinga, dan cara untuk menganalisa hasilnya.
Tapi, ternyata, ia gagal. Tahun 1894, seorang psikolog bangsa Prancis, Alfred Binet, mulai mencari-cari cara untuk mengukur kemampuan mengingat, mengkhayal, perhatian, kemampuan memahami kalimat, pertimbangan moral, dan fungsi mental rumit lainnya pada anak-anak. Tahun 1903, ia melaporkan hasilnya, penelitian intensif tentang perkembangan intelektual dua orang anak perempuannya sendiri. Karena itu, ketika tahun 1904 di Paris dibentuk suatu komisi untuk menangani anak-anak yang kurang normal, ia diminta untuk duduk dalam komisi tersebut.
Dengan bantuan Theodore Simon, Binet memberikan beragam jenis tes kepada anak-anak kurang normal itu. Ia memilih tes mana yang dapat membedakan anak-anak cerdas dari yang bodoh, atau anak-anak lebih tua dari yang muda. Tahun 1905, Binet dan Simon menyusun semua bahan-bahan tes itu berdasarkan tingkat kesulitannya, disebut Skala Metrik Inteligensi, suatu tes inteligensi pertama yang bermanfaat. Setiap anak dites menurut tingkat kesulitan itu, dari paling mudah sampai akhirnya tiba pada tes tersulit yang tidak dapat dilakukannya —ini lalu dibandingkan dengan kemampuan anak-anak lain. Versi baru tahun 1908 menggolongkan tes menurut umur, dari 3 sampai 13 tahun, dimana 50 sampai 75 persen anak-anak yang dites mampu mengerjakannya. Tahun 1911, diperb aiki lagi, memperluas usia yang dites sampai 15 tahun. Pada masa itu, anak umur 3 tahun di Prancis rata-rata dapat menunjuk hidungnya, matanya, dan mulutnya; mengulang bilangan sampai dua digit, menyebutkan benda dalam gambar menyebutkan nama keluarganya, dan mengulangi kalimat dari enam suku kata. Umur 15 tahun, mereka mampu mengulang angka 7 digit, mengulang kalimat dari 26 suku kata, menginterpretasikan gambar dan fakta. Tes itu dapat memisahkan usia mental anak-anak. Jadi, anak usia 3 tahun yang mampu melaksanakan tes untuk anak usia 5 tahun, disebut punya usia mental 5 tahun.
Asal-Usul IQ
Sumbangan Binet —konsep usia mental plus metoda untuk menentukannya— ini tidak berkembang dari teori inteligensi umum, tapi dari cara trial and error alias coba-coba. Sejak itu, pendekatan praktis semacam ini menjadi ciri untuk mengukur mental, menghasilkan tes yang tetap berfungsi walau tak seorangpun tahu mengapa begitu.
Menurut metoda Binet, keterlambatan mental merupakan perbedaan antara usia mental si anak dengan usia kronologisnya (sebenarnya); ketinggalan dua tahun merupakan kelainan yang serius. Tahun 1914, seorang psikolog bangsa Jerman, William Stem, menganjurkan membagi usia mental dengan usia kronologis untuk mendapatkan angka mental quotient. Jadi, pada contoh di atas, bila anak usia 3 tahun dapat mengerjakan tes untuk anak usia 5 tahun, quotientnya adalah 5/3 atau 1,66. Bila anak usia 4 tahun dapat mengerjakan tes untuk anak 4 tahun, quotient-nya adalah 4/4 atau 1. Quotient anak rata-rata adalah satu , anak yang quotient-nya di bawah satu berarti di bawah normal, dan anak yang quotient-nya lebih dari satu (di atas satu) adalah superior. Jika perbandingan ini dikalikan 100, akan dihasilkan IQ (intelligence quotient).
Di Amerika Serikat, Lewis Terman, seorang psikolog Universitas Stanford, menterjemahkan hasil karya Binet, mengembangkan norma bagi anak-anak Amerika, dan menerbitkan hasilnya pada tahun 1916 sebagai tes versi Stanford. Tak ada ide yang baru dalam versi ini. Dari mula, untuk mengukur, metoda IQ itulah yang dipakai. Ia bahkan yakin bahwa IQ tetap seumur hidup; jadi, inteligensi seorang dewasa, dapat diramalkan dari tes yang diberikan semasa kanak-kanak.
Tes inteligensi berkembang bak jamur di Amerika Serikat. Pengertian Binet mudah dipahami, dan tersedia beberapa versi yang tinggal dipilih. Langganan pertama yang paling penting adalah Angkatan Darat Amerika Serikat, yang mentes para pendaftar pada Perang Dunia I.
 Tapi, karena keperluan mendesak dan banyaknya pendaftar yang harus dites, Angkatan Darat AS tidak mempunyai cukup waktu untuk mengikuti tes Binet yang begitu intensif, mengamati orang satu per satu. Maka para psikolog, yang dikepalai Robert M. Yerkes, mengembangkan tes tertulis yang disebut Army Alpha. Tes ini, dibagikan kepada kelompok-kelompok besar orang dewasa, yang h arus dikerjakan dalam batas waktu tertentu. Versi pantomim, atau Almy Beta, ditujukan untuk orang-orang buta huruf atau yang tidak mengerti bahasa Inggris.
Tapi, karena keperluan mendesak dan banyaknya pendaftar yang harus dites, Angkatan Darat AS tidak mempunyai cukup waktu untuk mengikuti tes Binet yang begitu intensif, mengamati orang satu per satu. Maka para psikolog, yang dikepalai Robert M. Yerkes, mengembangkan tes tertulis yang disebut Army Alpha. Tes ini, dibagikan kepada kelompok-kelompok besar orang dewasa, yang h arus dikerjakan dalam batas waktu tertentu. Versi pantomim, atau Almy Beta, ditujukan untuk orang-orang buta huruf atau yang tidak mengerti bahasa Inggris.
Pengalaman Angkatan Darat AS itu menunjukkan betapa “luwesnya” tes itu: bisa dibuat dalam bentuk bagaimanapun , namun tetap mampu membedakan kemampuan setiap individu. Sejak itu, tes mental luas diterima masyarakat,sdianggap lumrah sudah oleh semua orang.
Ketika tes inteligensi pertama kali dikenal, keyakinan orang terhadap faktor keturunan begitu kuat dan meluas. Jika tanaman dan binatang dapat dibiakkan dan disaring untuk mendapatkan sifat-sifat yang unggul, kata orang masa itu, mengapa manusia tidak? Tes inteligensi memberi metoda objektif kepada para penganut eugenik (perbaikan ras manusia), —untuk mengidentifikasi pribadi-pribadi yang superior dan yang inferior— sehingga prograrn mereka dapat dilaksanakan. Tujuannya? Membentuk manusia-manusia unggul, dan membunuh, mensterilkan atau mencegah berkembangbiaknya orang-orang yang tidak dikehendaki, misalnya yang memiliki penyakit epilepsi (ayan) dan lemah mental.
Jika inteligensi seseorang sudah ditentukan sejak lahir, seperti keyakinan para pendukung eugenik, pengalaman tentu tak bisa mengubahnya. Bahkan belajar itu tak ada gunanya, bukan? Toh ia tak bisa mengubahnya, karena IQ dianggap tak berubah selama hidup. Ketika banyak bukti menunjukkan bahwa IQ bisa ditingkatkan dengan pen didikan khusus, atau dapat juga berkurang karena adanya hambatan-hambatan seperti belum mengerti/mengenal bahan atau bahasa yang digunakan dalam tes itu, mereka sekedar menganggap bahwa tes itu sendiri yang masih belum baik; harus diganti dengan bahan lain yang bebas budaya dan tak terpengaruh oleh proses belajar. Tapi, penggantian dengan bahan semacam itu, tentu menyesatkan. Karena siapa yang bisa membuat tes yang tidak tergantung pada informasi —atau pengetahuan?
Persoalan ilmiah tentang penurunan kecerdasan ini, tentu lebih mudah dipecahkan, jika tidak dipersulit dengan adanya masalah diskriminasi dan prasangka ras. Sebagai contoh, tak dapat dipungkiri, bahwa di AS orang negro rata-rata 15 angka lebih rendah dalam tes inteligensi ketimbang kulit putih. Yang menjadi masalah adalah bagaimana menafsirkan fakta itu. Perbedaan itu bisa saja dianggap bukti sebagai akibat dari efek diskriminasi, yang dialami orang-orang negro sejak dulu dalam kehidupannya sehari-hari. Tapi, ketika perbedaan ini diketemukan pada tes calon tentara di dalam Perang Dunia I itu, ia langsung ditafsirkan sebagai bukti bahwa inteligensi itu diwariskan, bahwa orang negro memang lebih bodoh.
Lebih jauh lagi, kebijakan kemasyarakatan dianjurkan atas dasar keturunan yang salah itu. Terman, misalnya, menganjurkan agar pendidikan anak negro dan Meksiko harus dipisahkan dalam kelas khusus tersendiri, sehingga mereka dapat diarahkan menjadi pekerja efisien alias tukang walau tak mampu menguasai hal-hal yang menuntut pikiran/imajinasi. Sayang, ide semacam ini tersebar luas, menjadi
senjata bagi orang-orang tertentu untuk mengukuhkan sifat diskriminasi mereka. Jadi, tak mengherankan, kalau tes mental dirasakan banyak orang sebagai satu alat tambahan diskriminasi ras, sehingga timbul suara-suara untuk menghapus semua bentuk tes semacam itu.
Pendapat bahwa inteligensi itu sifat turunan men-jadi semakin kabur dalam tahun 1970an, ketika salah satu pendukung-nya, orang Inggris Sir Cyril kan data yang menunjukkan kesamaan tingkat IQ pada 2 anak kembar yang telah dipisahkan sejak lahir. Yang lebih mengherankan, ketimb ang penipuan si Burt ini, banyak yang mengaku bahwa data Burt itu (yang jelas-jelas palsu) mendukung bahkan memastikan kebenaran ide-ide mereka sendiri! Tetap saja, banyak psikolog yang masih yakin, bahwa perbedaan dalam nilai tes mencerminkan perbedaan inteligensi sebuah ras.
Walau kebanyakan kritik terhadap tes kemampuan ke- banyakan tertuju pada penyalahgunaan hasil tes, tes itu sendiri bukannya tidak dikecam. Bahkan meskipun penyusunan tes modem kini menggunakan metoda analisa statistik paling mutakhir, dan bahan-bahan pengujian yang telah disepakati keandalan dan kebenarannya. Sebabnya, maka dikecam, karena cara penyusunan secara pragmatis ini memang masih sering menghasilkan bahan tes yang kurang bermutu dan kurang relevan, walau sudah dipikirkan hati-hati. Masalahnya adalah, bahwa teknologi pengujian inteligensi itu, berkembang tanpa adanya dukungan teori yang kuat. Bahkan masalah-masalah dasar, seperti seberapa banyak jumlah kemampuan yang berbeda, belum juga pasti. Di lain pihak, kini mulai disadari, bahwa tingkat IQ tidak selalu menjamin keberhasilan seseorang dalam pendidikan maupun di masyarakat. Masih ada kemampuan lain yang jarang diukur, misalnya kreativitas seseorang, yang banyak menentukan masa depannya (lihat AKU TAHU/ Agustus ’84 hal 46). Juga, ada tanda-tanda menggembirakan bahwa teori mulai mengejar praktek. Para psikolog kognitif telah mulai memperinci sifat proses-proses mental yang terlibat dalam perilaku inteligensi. Psikolog Swiss, Jean Piget, yang lebili banyak mengembangkan penelitiannya berdasarkan teori formal, telah memperinci 4 tahap perkembangan dalam inteligensi.
Namun, sementara itu, masyarakat kini telah terlanjur terbiasa mengandalkan diri pada tes inteligensi untuk membantu mengambil keputusan mengenai kemajuan pendidikan, bakat seseorang, pemilihan pegawai, dan sebagainya. Meskipun tanpa bukti teoritis, penggunaan tes akan tetap ada dalam berbagai bentuknya. Dan selama tes semacam ini terus berlanjut, kita perlu menjaga kemungkinan penyalahgunaan hasil-hasil tes itu.– G.A. Miller
Sumber: Majalah AKU TAHU/ Maret 1986