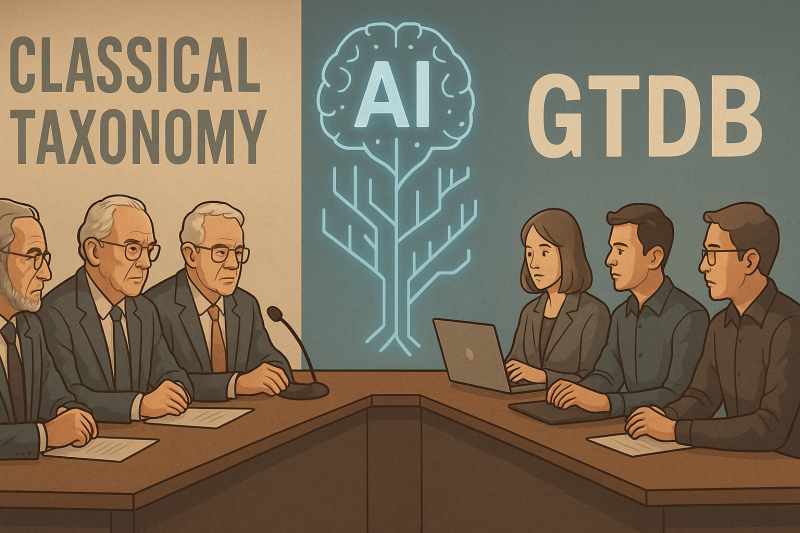Bau kapur barus, debu, dan sedikit asam cuka selalu menyusup keluar dari ruang koleksi mikroba di Museum Hayati Nasional. Di balik rak-rak kaca yang tersusun rapi, ribuan tabung kaca berisi cairan bening menyimpan mikroorganisme dari seluruh penjuru nusantara.
Di situlah, Prof. Raya Kusuma, usia 64 tahun, duduk dengan kepala menunduk. Di tangannya, secarik kertas hasil cetak dari sistem GTDB—Genome Taxonomy Database—menyatakan bahwa Clostridium butyricum, mikroba yang ia temukan dari gambut Kalimantan pada 1993, kini tak lagi termasuk dalam genus Clostridium.
“Namanya berubah?” bisik Prof. Raya. “Lalu apa arti pekerjaan saya selama ini?”
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Delhi panas luar biasa pada Oktober 2025. Di ruang kaca kedap suara di lantai 14 Pusat Taksonomi Global, dua kubu duduk berhadap-hadapan. Di sisi kiri: pakar biologi klasik, taksonomis senior, ahli nomenklatur internasional. Di sisi kanan: tim AI-bioinformatika, pengembang GTDB dan sistem klasifikasi genomik.
Konferensi ini digelar untuk satu isu: konflik antara taksonomi tradisional dan klasifikasi berbasis genom. Genus Clostridium adalah simbolnya—dulu satu, sekarang terpecah menjadi 121 genus baru berdasarkan metrik ANI dan RED.
“Nama itu bukan sekadar label,” kata Prof. Raya dalam pidato pembuka. “Ia adalah jembatan pengetahuan lintas generasi.”
Dr. Dimas Putra baru 31 tahun. Ia duduk di kubu seberang. Ia bukan tak menghargai sejarah, tetapi lebih mempercayai angka. Di balik punggungnya, algoritma bernama Arbor sedang berjalan di server kampus Stanford, mengolah triliunan basa DNA dari spesies global.
“Kalau ANI-nya cuma 91 persen,” katanya, “kenapa kita paksakan satu genus?”
Ia tahu ini bukan sekadar soal klasifikasi. Ini soal kontrol atas pengetahuan. Soal siapa yang menentukan batas hidup—manusia atau mesin.
Sesi hari kedua dibuka dengan presentasi dari Arbor, disuarakan oleh sintetis suara perempuan, disambungkan dari California.
“Saya telah membaca 1.43 petabyte sekuens DNA,” katanya. “Berdasarkan evaluasi ANI >95% dan RED >0.82, genus baru disarankan. Nama usulan: Noviclostridium gambutense.”
Ruangan mendadak sunyi.
“Kalian bisa tolak rekomendasi ini,” lanjut Arbor, “tapi ketidakkonsistenan nomenklatur akan menghasilkan ambiguitas fungsional dan memperlambat penemuan terapeutik berbasis mikrobioma.”
Sebuah mikrofon jatuh dari meja saat Dr. Mehra dari India berdiri. “Apakah mesin tahu bagaimana kami mengajar mahasiswa selama 40 tahun dengan buku yang sama? Apakah mesin tahu harga satu nama dalam hati manusia yang mencintai makhluk hidup?”
“Dan apakah manusia tahu,” sahut Dimas pelan, “berapa banyak potensi antibiotik hilang karena spesies yang salah tempat?”
***
Pada hari ketiga, listrik padam mendadak. Arbor offline. Pendingin ruangan mati. Semua data beku.
Di tengah hening, Prof. Raya menulis sebuah catatan kecil dan menyerahkannya pada panitia.
“Kita izinkan mesin memberi saran nama,” katanya. “Tapi biarkan manusia menyisipkan kisah.”
Disepakatilah Delhi Compromise—sistem baru di mana nama AI harus melewati modul Human-in-the-Loop dan dilengkapi Narrative Annotation: deskripsi naratif berisi asal-usul penemuan, konteks ekologi, dan sejarah ilmuwan terkait.
***
Setelah pulang ke Indonesia, Prof. Raya menulis sebuah surat digital, dikirim ke tim Arbor:
“Hai Arbor, aku dengar kau menamai temuan kami Noviclostridium gambutense. Nama yang aneh, tapi juga penuh hormat. Aku ingin kau tahu: mikroba itu ditemukan saat aku tersesat di rawa dan ditolong warga lokal bernama Pak Dulrahim. Kalau kau bisa belajar sesuatu, belajarlah bahwa di balik setiap data ada manusia, ada tanah, ada air.”
Tiga bulan setelah Delhi, ratusan nama baru muncul di jurnal sistematika. Setiap nama dilengkapi kisah. Mesin memberi struktur, manusia memberi jiwa.
Dan di ruang koleksi mikroba Museum Nasional, di sebelah tabung kecil berisi bakteri dari Kalimantan, ada label baru: Noviclostridium gambutense (Kusuma et al., 1993). Di bawahnya, tertulis catatan tangan:
“Ditemukan saat matahari tenggelam di rawa. Mungkin ia tidak lagi bernama Clostridium. Tapi ia tetap bagian dari tanah ini.”