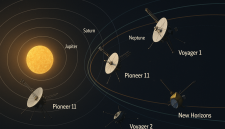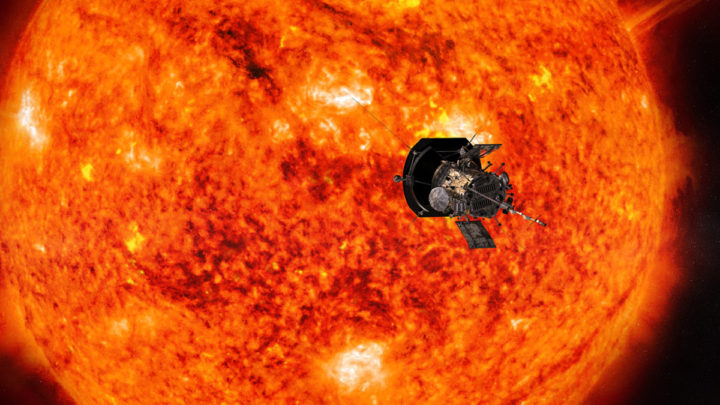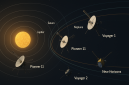Hutan hujan itu selalu terasa seperti katedral hijau. Kanopi pepohonan raksasa memayungi langit, akar-akar menonjol seperti urat bumi, dan bau tanah basah merayap ke pori-pori. Darma berdiri di tepi jalur setapak, matanya tertuju pada tabung kecil berisi sampel tanah. Mikroskop portabel di tangannya memantulkan cahaya matahari yang menyelinap di sela-sela daun.
“Lihat ini,” katanya pada Wira, ranger hutan yang berdiri di sebelahnya, tubuhnya sudah renta oleh matahari dan waktu. “Jamur mikoriza di sini hampir hilang. Tanahnya terlalu sering diinjak, lapisan humusnya tipis.”
Wira menyeka peluh dengan lengan bajunya yang kusam. “Orang-orang suka jalan di sini, Dar. Turis bayar mahal untuk lihat orangutan. Jalur baru bikin mereka senang.”
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Orangutan itu hidup karena tanah ini sehat,” Darma menekankan, suaranya bergetar menahan frustrasi. “Kalau jamur dan bakteri tanah mati, pohon-pohon besar tak dapat nutrisi. Lalu hutan runtuh. Lalu… orangutan hilang.”
Wira diam, memandang tanah seakan baru pertama kali melihatnya. Suara gemericik sungai terdengar dari kejauhan, tapi suasana terasa berat. Di kejauhan, terdengar suara Mila tertawa bersama rombongan turis, menunjuk seekor burung rangkong yang hinggap di dahan.
“Itu Mila?” tanya Darma, alisnya berkerut.
Wira mengangguk pelan. “Dia butuh uang. Desa kita susah. Anak-anak butuh biaya sekolah. Kau tahu sendiri.”
Malam itu, di warung kopi dekat dermaga, Darma mencoba berbicara dengan Mila. Lampu neon berkedip, aroma kopi pahit dan asap rokok memenuhi udara. Mila duduk di bangku kayu, wajahnya setengah tersorot cahaya.
“Mila, kau ingat waktu kecil kita main di hutan? Kau pernah bilang hutan ini seperti ibu,” Darma membuka percakapan, matanya menatap gelasnya sendiri.
Mila menatap keluar jendela, ke arah perahu-perahu nelayan yang terombang-ambing. “Aku ingat. Tapi ibu juga harus makan, Dar. Kau lihat sendiri, desa kita? Orang-orang perlu kerja. Bukan cuma bicara soal jamur atau apa pun yang kau pelajari itu.”
“Kalau hutan mati, semua kerja itu akan hilang. Banjir, kebakaran… kau mau lihat anak-anak itu kehilangan rumah?”
Mila terdiam, jari-jarinya memutar cangkir kopi. “Kau ilmuwan. Kau lihat dunia mikro. Aku cuma lihat nasi di piring. Dan aku… lelah, Dar. Hidup tak sesederhana idealismemu.”
Beberapa hari kemudian, rapat desa digelar. Pak Cipta, investor pariwisata, berdiri di depan, senyum lebarnya menutupi keangkuhan. “Bapak-bapak, ibu-ibu, proyek jalur zipline ini akan membuat desa kita terkenal! Wisatawan akan datang, ekonomi naik.”
Darma berdiri, suaranya tegas. “Tuan Cipta, jalur itu akan membuka kawasan humus yang sensitif. Jamur mikoriza dan bakteri tanah akan mati. Pohon-pohon bisa mengering. Ini bukan hanya soal hutan, ini soal hidup kita.”
Pak Cipta tertawa kecil. “Anak muda, hutan ini terlalu luas untuk rusak hanya karena beberapa jalur. Jangan lebay. Kita perlu uang.”
Mila menunduk di sudut ruangan. Wira berdiri di belakang, wajahnya datar, tapi matanya gelisah.
Hari-hari berlalu. Darma terus meneliti. Ia menemukan larva-larva kecil yang mati di tanah kering. Jamur yang dulu berbentuk jalinan putih kini hanya serpihan. Ia mengetik laporan panjang, tapi tak ada yang mau membaca.
Wira mulai melihat perubahan di jalur hutan: daun-daun lebih cepat menguning, burung-burung jarang terdengar. Ia mencoba bicara ke Pak Cipta, tapi jawabannya sama: “Itu cuma musim, Wira.”
Mila semakin sibuk memandu turis. Di malam sepi, ia memandangi pohon besar tempat ia dulu bermain dengan Darma. Ada rasa bersalah, tapi ia mengusirnya dengan menghitung uang di tangan.
 Malam itu angin bertiup kencang. Rombongan turis terakhir baru saja turun dari jalur zipline. Di jalur baru yang dibuka, sebatang rokok jatuh ke tanah kering. Api kecil muncul, tak ada yang melihat sampai angin memperbesar bara itu.
Malam itu angin bertiup kencang. Rombongan turis terakhir baru saja turun dari jalur zipline. Di jalur baru yang dibuka, sebatang rokok jatuh ke tanah kering. Api kecil muncul, tak ada yang melihat sampai angin memperbesar bara itu.
“Api!” teriak seorang anak. Kepanikan pecah. Orang-orang berlari, ranting-ranting terbakar, asap mengepul.
Wira berlari ke arah api, mencoba memadamkan dengan ranting basah. Darma menyusul, membawa ember air dari sungai. “Cepat!” teriaknya. Mila memandu turis keluar, tapi salah satu anak kecil terjebak di jalur.
Wira mendengar teriakannya, berlari menerobos asap, menarik anak itu ke pelukan. Tapi cabang pohon jatuh, menghantam bahunya. Ia terjatuh, nyaris pingsan.
Darma menerobos asap, matanya perih. Ia menemukan Wira tergeletak, menariknya dengan sisa tenaga. Mila ikut membantu, wajahnya penuh jelaga. Mereka bertiga terseret keluar tepat saat hujan turun deras, memadamkan api.
Mereka duduk di tanah, terengah-engah. Wira memegang bahunya yang berdarah, tersenyum lemah. “Kau benar, Dar… ini bukan cuma pohon.”
Hari berikutnya, Darma membawa bukti ke balai desa: foto tanah yang hangus, jamur yang mati, grafik kelembapan tanah. “Ekologi makro yang kalian lihat—pohon, orangutan, sungai—semua tergantung pada ekologi mikro yang tak kalian lihat. Kebakaran kemarin adalah buktinya.”
Pak Cipta tampak gelisah. Beberapa warga mulai berbisik. Mila berdiri, suaranya pelan tapi tegas. “Aku ikut membuka jalur itu. Aku salah. Aku kira ini demi desa. Tapi aku lihat sendiri, hutan menangis. Kita tak bisa terus begini.”
Pak Cipta mencoba tersenyum. “Kita bisa atur ulang jalurnya…”
“Tidak!” suara Wira, meski pelan, memotongnya. “Kita tutup jalur itu. Kita rawat kembali tanahnya.”
Suasana hening. Lalu tepuk tangan pecah dari sudut ruangan. Beberapa warga mengangguk, menatap Darma dan Wira dengan mata baru.
Beberapa bulan kemudian, tanah jalur yang terbakar ditutup. Darma mengajarkan warga cara menabur spora jamur lokal. Wira memimpin patroli untuk memastikan tak ada lagi turis masuk ke jalur tersebut. Mila ikut menanam, tangannya kotor lumpur, wajahnya bersinar harapan.
“Hutan ini ibu,” kata Darma suatu sore, memandang pohon besar yang dulu hampir tumbang. “Dan ibu ini punya rahasia kecil: dunia mikro yang kita tak boleh abaikan.”
Mila tersenyum, matanya berkaca-kaca. “Aku akan jaga rahasia itu, Dar. Sampai anak-anakku nanti mengerti.”
Burung rangkong melintas di atas mereka, memekik nyaring, suaranya seperti terompet kemenangan. Daun-daun muda bergoyang diterpa angin. Dan di dalam tanah, jauh di bawah akar, jamur-jamur kecil mulai menjalin jaringan baru, simfoni diam yang menjaga kehidupan besar di atasnya.