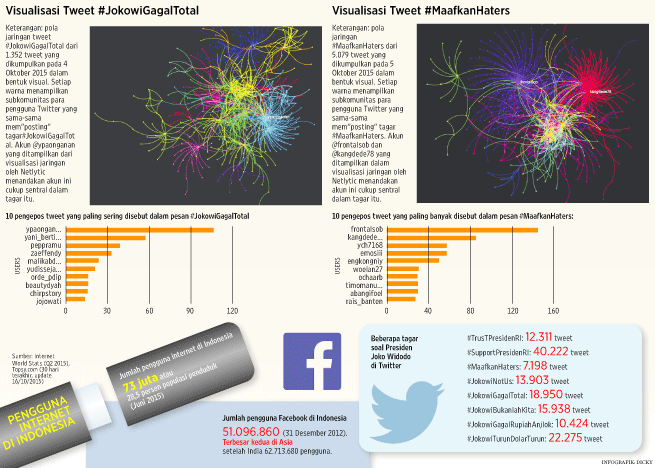Pada 20 Oktober esok hari, sudah genap satu tahun Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dilantik menjadi nakhoda negeri ini. Namun, di dunia maya, jejak-jejak “perang” dukungan semasa Pemilihan Presiden 2014 masih berakar kuat. Kini muncul kecenderungan polarisasi sikap netizen terhadap pemerintah. Akankah ini menjadi ancaman demokrasi digital di Indonesia?
Selama masa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014, diskusi soal pasangan calon presiden dan calon wakil presiden berlangsung panas di media sosial. Netizen atau pengguna internet saling berbagi tautan informasi soal pasangan calon. Mereka juga bertukar komentar. Berbagai kreativitas di dunia maya yang muncul menunjukkan masyarakat aktif dalam perhelatan pilpres.
Di sisi lain, tidak jarang netizen saling meng-unfriend atau meng-unfollow akun yang punya pandangan politik berbeda. Fachri (30), warga Yogyakarta, termasuk netizen yang aktif menyebar konten calon presiden pada pilpres lalu. Tidak jarang, karyawan sebuah perusahaan ini berdebat sengit dengan teman- temannya di Facebook. Belakangan, teman-teman yang berseberangan pendapat dengannya memblok akun Fachri. Dengan demikian, mereka tak perlu melihat status-statusnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Irma Priyadi (35) mengalami hal serupa. Hanya saja, ibu rumah tangga yang tinggal di Bogor, Jawa Barat, ini tak ambil pusing. Dia mengaku tak mudah mengubah pandangan netizen yang sudah telanjur suka atau telanjur benci pada kandidat pasangan calon tertentu. Polarisasi dukungan tak sulit diamati karena saat itu hanya ada dua pasangan calon. Setelah pilpres, polarisasi dukungan tak kunjung surut. Diskusi di dunia maya bergeser dari awalnya siapa di antara kedua tokoh itu yang paling layak memimpin menjadi pro dan kontra terhadap sepak terjang pemerintahan Jokowi-Kalla.
Beberapa pekan jelang setahun pemerintahan Jokowi-Kalla, di media sosial, baik di Facebook maupun di Twitter, bisa dengan mudah ditemui diskusi yang kontra ataupun mendukung pemerintahan Jokowi-Kalla. Di Twitter, sejak akhir September bisa ditemui tagar seperti #JokowiGagalTotal atau #JokowiNotUs.
Dari hasil penelusuran di layanan analisis media sosial Topsy, ada 18.950 kicauan yang memuat tagar #JokowiGagalTotal. Sementara tagar #JokowiNotUs di-tweet 13.903 kali sebulan terakhir. Akun @AlfinLogaritma, misalnya, menulis “cie di abang foto sendiri di tengah kebakaran hutan. Pencitraan mulu bang. Mending turunin harga dolar sono. Jalan2 mulu#JokowiGagalTotal”. Akun @Ginggar_GK menulis “dunia usaha kian menjadi sulit phk massal segera terjadi#JokowiGagalTotal”.
Sebagai respons dari tagar-tagar di atas, lantas muncul tagar yang mendukung Jokowi-Kalla, seperti #MaafkanHaters dan #SupportPresidenRI. Topsy mencatat tagar #MaafkanHaters di-tweet 7.198 kali selama 16 September hingga 16 Oktober. Sementara tagar #SupportPresidenRI dikicau 40.222 kali. Akun @FrontalSob, misalnya, berkicau, “ketika makian dibalas dengan memaafkan. Keren lah #MaafkanHaters”. Akun @Dicky_Pandawa menulis, “mereka yang menghina, mereka yang membuat medianya, mereka sendiri yang percaya.#MaafkanHaters”.
Pengajar Sosiologi Komunikasi di Universitas Diponegoro Semarang, Triyono Lukmantoro, mengatakan, seharusnya setahun setelah pilpres, masyarakat menjadi lebih dewasa dalam berdemokrasi di dunia maya. Diskusi di media sosial, baik pihak yang pro maupun kontra kepada pemerintahan terpilih, seharusnya berdasar pada rasionalitas kritis. Artinya, penilaian terhadap kinerja pemerintah didasarkan pada logika, bukan sekadar berdasar suka atau tidak suka.
“Media sosial itu bukan sekadar ruang berekspresi, tetapi diandaikan sebagai ruang publik. Di ruang publik, seseorang berkata-kata, mencerna, menggunakan rasionalitas. Sekarang yang kerap muncul sekadar saling mencela, saling serang antara pendukung yang pro dan yang kontra,” kata Triyono.
Polarisasi dukungan
Media sosial telah menyediakan ruang-ruang publik di dunia maya untuk mendiskusikan berbagai hal, termasuk politik. Media sosial, menurut Jae Kook Lee dan kawan-kawannya (2014) dalam Social Media, Network Heterogeneity, and Opinion Polarization, membuat orang bisa dengan bebas tanpa sekat waktu dan ruang “terpapar” pandangan yang berbeda. Informasi yang berbeda membuat seseorang menjadi lebih toleran dalam menerima perbedaan pandangan.
Namun, di sisi lain, muncul pula kekhawatiran media sosial justru menghasilkan masyarakat yang kian terpecah-pecah akibat polarisasi pandangan di dunia maya. Hal ini yang sebenarnya juga sudah dikhawatirkan para peneliti media sosial dan demokrasi di negara-negara Barat.
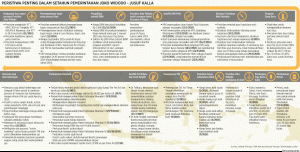 Peter Dahlgren (2009) dalam Media and Political Engagement menyebut polarisasi itu sebagai dampak dari “cyberghettos” atau “ghetto-ghetto” siber, merujuk konsep “ghetto” di ranah offline yang bermakna perkampungan terisolasi. Di tulisan yang sama, ia juga meminjam istilah lain, yakni “kepompong informasi”. Anatoliy Grudz dan Jeffrey Roy (2014) dalam Investigating Political Polarization on Twitter: A Canadian Perspective menggunakan istilah “bilik gema”.
Peter Dahlgren (2009) dalam Media and Political Engagement menyebut polarisasi itu sebagai dampak dari “cyberghettos” atau “ghetto-ghetto” siber, merujuk konsep “ghetto” di ranah offline yang bermakna perkampungan terisolasi. Di tulisan yang sama, ia juga meminjam istilah lain, yakni “kepompong informasi”. Anatoliy Grudz dan Jeffrey Roy (2014) dalam Investigating Political Polarization on Twitter: A Canadian Perspective menggunakan istilah “bilik gema”.
Seluruh istilah itu merujuk pada kecenderungan seseorang untuk mencari informasi yang sesuai dengan pandangan mereka. Media sosial menyediakan kemungkinan itu dengan adanya fitur-fitur untuk mengikuti orang-orang yang disukai lalu mendepak yang berbeda pandangan. Lama-kelamaan, seseorang semakin terisolasi dalam “ghetto” masing-masing di dunia maya sehingga memunculkan pandangan yang semakin ekstrem.
Apakah hal ini juga terjadi di Indonesia? Triyono Lukmantoro khawatir pola hubungan netizen di dunia maya setahun terakhir mulai terpolarisasi. Menurut dia, netizen bisa dibagi dalam dua kategori besar antara pendukung yang membela habis-habisan dan netizen yang kontra lantas menjelek-jelekkan pemerintahan Jokowi-Kalla.
Analisis awal terhadap 1.352 tweets dengan tagar #JokowiGagalTotal dan 5.079 tweets bertagar #MaafkanHaters menggunakan Netlytic alat analisis media sosial cenderung mengonfirmasi kekhawatiran Triyono. Ada tendensi pola interaksi berpusat pada beberapa netizen tertentu.
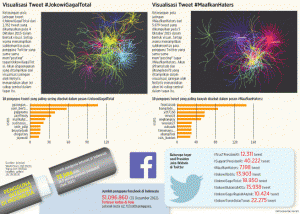 Selain itu, dari penelusuran acak terhadap kicauan antar-netizen tampak kecenderungan akun yang kerap berkomentar positif terhadap pemerintah terhubung dengan akun-akun berkarakter serupa. Sementara akun yang kontra pemerintah lebih banyak terhubung dengan akun yang juga sering menyuarakan pendapat senada.
Selain itu, dari penelusuran acak terhadap kicauan antar-netizen tampak kecenderungan akun yang kerap berkomentar positif terhadap pemerintah terhubung dengan akun-akun berkarakter serupa. Sementara akun yang kontra pemerintah lebih banyak terhubung dengan akun yang juga sering menyuarakan pendapat senada.
Kendati ada dua kutub besar yang pro dan kontra, dalam beberapa kasus juga terlihat interaksi antar-netizen dari dua kutub berbeda. Sayangnya, interaksi itu sebagian bernada negatif dan saling serang. Argumentasi itu masih bersifat anekdotal. Tentu diperlukan penelitian lebih jauh sebelum membuat kesimpulan soal pola hubungan netizen di dunia maya. Hanya saja, argumentasi itu bisa dijadikan bel peringatan bagi netizen dan pegiat demokrasi digital di Indonesia.
Pasalnya, seperti disampaikan Jae Kook Lee dan kawan-kawannya, polarisasi yang kian ekstrem bisa menjadi ancaman serius bagi demokrasi. Ini karena netizen yang semakin terfragmentasi dalam “ghetto-ghetto” politik di dunia maya jadi kehilangan “pijakan” yang sama di ruang publik. Mereka juga cenderung jadi semakin tak toleran terhadap perbedaan pandangan.
Moderasi sikap
Kendati demokrasi digital di Indonesia menghadapi tantangan tersebut, Dhenok Pratiwi, Campaign Associate Change.org, yang juga aktivis Forum Demokrasi Digital Indonesia, masih menaruh asa pada tumbuhnya budaya partisipasi politik dunia maya yang sehat. Dhenok optimistis, kesempatan mewujudkan diskursus rasional di ruang publik maya terbuka. Namun, netizen harus mampu memanfaatkan teknologi yang ada untuk tidak menelan mentah-mentah informasi yang disebar di media sosial.
“Sekarang banyak muncul platform untuk membantu publik mengklarifikasi informasi dan data,” ujar Dhenok Pratiwi.
Selain harus pandai menyaring informasi, Triyono juga menilai perlu upaya mendorong netizen bersikap moderat. Hal ini bisa dimunculkan oleh politisi-politisi muda yang juga aktif di dunia maya. Mereka harus mampu mengajak netizen untuk tidak melihat pemerintah atau politik di dunia maya secara hitam-putih. Namun, melihat berbagai segi secara kritis.
Tentu perlu diingat media sosial itu merupakan alat. Ia tidak otomatis berdampak positif atau negatif terhadap demokrasi. Seperti halnya pistol. Di tangan polisi yang bersih dan jujur, pistol bisa memberi rasa aman. Namun, di tangan penjahat keji, pistol itu menebar teror. Nah, di tangan Anda, akan jadi apa media sosial dan masa depan demokrasi digital Indonesia? (ANTONY LEE)
——————-
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 19 Oktober 2015, di halaman 2 dengan judul “Ancaman “Ghetto-Ghetto” Siber Seusai Pilpres”.