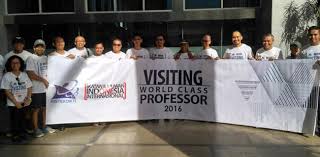Kementerian Ristek dan Dikti menegaskan dalam Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2017 bahwa dalam kurun tiga tahun (2015-2017) seorang guru besar harus menghasilkan tiga karya ilmiah di jurnal internasional atau satu karya ilmiah di jurnal bereputasi (Kompas, 6/2).
Jika ketentuan itu tak dipenuhi, tunjangan kehormatan guru besar akan dihentikan (Kompas, 31/1). Basis data Scopus (yang dimiliki Penerbit Elsivier) yang mengindeks artikel di jurnal ilmiah bereputasi menjadi momok bagi akademisi Indonesia, baik guru besar maupun nonguru besar, khususnya lektor kepala yang berniat menjadi guru besar. Kebijakan ini telah menimbulkan kehebohan dan kontroversi.
Keharusan guru besar dan lektor kepala menulis karya ilmiah di jurnal bereputasi dilatarbelakangi keinginan pemerintah dan universitas untuk menjadi world class university. Padahal, pemeringkatan universitas cenderung ideologis dengan parameter obyektif-kuantitatif dan syarat khusus tak tertulis (seperti dana yang besar) yang belum tentu bisa dipenuhi universitas kita.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Paradigma pemeringkat universitas seperti Webometrics, QS World University Ranking dan QS Stars bersifat “etnosentrik” yang menekankan keseragaman alih-alih keunikan universitas. Selama karya ilmiah harus berbahasa Inggris, bukan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia. Sampai kiamat kita tak akan mampu menyaingi universitas yang sudah berabad-abad menggunakan bahasa Inggris. Kita bahkan sulit menyaingi produktivitas ilmiah Malaysia dan Singapura yang lebih menguasai bahasa Inggris. Tujuan utama universitas adalah menghasilkan lulusan yang diserap pasaran kerja dan berkontribusi terhadap pembangunan bangsa, tak peduli apakah universitas itu berkelas dunia atau internasional. Bukankah tujuan akhir pendidikan adalah kemaslahatan umat manusia?
Lembaga pengindeks atau penerbit jurnal internasional sering dituduh kapitalistik. Tak jarang penulis harus membayar uang ratusan dollar AS per artikelnya. Kalaupun tidak, artikel jurnal itu dijual oleh penerbit kepada pengguna. Selain memperkaya penerbit dan negara di mana penerbit itu berada, akademisi kita yang menghasilkan pengetahuan (apalagi tentang Indonesia) justru memperkaya pengetahuan negara lain yang sudah maju.
Maka, kesenjangan ekonomi dan kesenjangan pengetahuan kedua negara justru semakin melebar. Sering syarat pemuatan artikel termasuk penyerahan hak cipta sehingga penulis tak bebas memasyarakatkan karyanya.
Pesimistis
Saya pesimistis kebijakan Kementerian Ristek dan Dikti seperti disebut pada awal tulisan ini akan berjalan mulus. Tak mudah memutuskan apakah tunjangan kehormatan mereka akan diteruskan atau dihentikan berdasar produktivitas ilmiah mereka.
Jika mau adil, setiap karya ilmiah dibobot berdasarkan peringkat jurnal yang memuatnya, termasuk jurnal nasional, bukan hanya jurnal internasional terindeks Scopus. Jika perlu berdasarkan mutu karya ilmiah, terlepas dari jurnal yang memuatnya. Jika semua guru besar dan lektor kepala yang ingin menjadi guru besar harus menulis di jurnal terindeks Scopus, belum tentu jumlah jurnal terindeks Scopus itu memadai untuk menampung semua artikel mereka meski kualitasnya bagus. Selain itu, butuh setidaknya setahun sejak artikel dikirim ke jurnal hingga pemuatan melalui beberapa kali pengembalian untuk dikoreksi.
Ada soal lain. Mengapa buku teks berkualitas yang dihasilkan akademisi tidak diperhitungkan? Jumlah pembaca buku teks kemungkinan besar lebih banyak daripada pembaca artikel di jurnal internasional karena lebih mudah diakses dan dipahami dan lebih memperlancar pembelajaran. Bukankah suatu karya tulis, buku maupun artikel, menjadi bermakna jika dibaca? Saya tahu seorang guru besar yang telah menulis belasan buku teks dan telah dicetak ulang berkali-kali dalam 25 tahun terakhir dan lima karya ilmiah di lima jurnal internasional, termasuk tiga jurnal terindeks Scopus, dalam dua tahun terakhir. Namun, ia lebih bangga bukunya dibaca dan dikutip ribuan orang di Indonesia dan Malaysia daripada artikel di jurnal internasional.
Sebagaimana buku, tidak semua artikel di jurnal terindeks bagus. Maka, buku teks bermutu yang dihasilkan akademisi seyogianya dipertimbangkan sebagai bagian dari produktivitas, apalagi jika ditulis berdasarkan riset, disiapkan matang, digunakan di berbagai perguruan tinggi, dan cetak ulang berkali-kali.
Jurnal vs buku
Menurut Martin Davis, profesor hukum di Universitas Melbourne, Australia, buku teks tak mudah ditulis. Namun, buku teks sering berkontribusi lebih signifikan dan lebih efektif bagi dunia ilmu daripada artikel di jurnal. “Memang budaya akademia agak bebal karena menganggap jurnal berimpak lebih penting,” kata Bary Turner, dosen senior di Universitas Lincoln, Inggris.
Mana yang lebih berbobot, artikel di jurnal atau buku teks, bergantung pada pola pikir dan parameter yang digunakan.
Kementerian Ristek dan Dikti seyogianya mengkaji ulang standar penilaian karya ilmiah akademisi Indonesia untuk guru besar dan calon guru besar. Misalnya, apakah aturan sepenuhnya diberlakukan bagi guru besar yang telah menulis sejumlah buku dan artikel di jurnal bereputasi (termasuk yang terindeks Scopus) dengan h-index (ukuran produktivitas dan dampak sitasi publikasi seorang akademisi) relatif tinggi? Seperti di peringkat Google’s Scholars meski selama tiga tahun terakhir (2015-2017) tak menghasilkan sejumlah karya ilmiah seperti yang disyaratkan Permen No 20/2017. Dengan kata lain, persyaratan itu mungkin lebih sesuai bagi mereka yang belum atau baru menghasilkan sedikit karya ilmiah, baik buku teks maupun artikel di jurnal bereputasi dengan h- index rendah.
Ada solusi berupa pelatihan, tetapi kalaupun dilakukan, sering pelatihan berlangsung satu dua sesi, paling banter dua hari. Ini sama sekali tak memadai karena keterampilan menulis karya ilmiah, apalagi berbahasa Inggris, harus diperoleh melalui pelatihan yang akhirnya menjadi kebiasaan dan keterampilan.
Berjenjang
Pelatihan atau lokakarya sebaiknya dilakukan berjenjang, bergantung pada tingkat kemampuan berbahasa Inggris. Dari empat kemampuan bahasa Inggris: berbicara, mendengarkan, membaca, dan menulis, kemampuan menulis biasanya paling rendah.
Kementerian Ristek dan Dikti seyogianya menyediakan dana pelatihan atau lokakarya penulisan itu. Dengan durasi belasan hingga puluhan jam per pekan sesuai kemampuan penulisnya.
Pengamatan menunjukkan, jangankan keterampilan menulis dalam bahasa Inggris, keterampilan sebagian besar akademisi menulis dalam bahasa Indonesia pun berantakan. Maka, salah satu alternatifnya, selain penulisan karya ilmiah dalam bahasa Inggris oleh akademisi bersangkutan, adalah penerjemahan karya ilmiah mereka ke dalam bahasa Inggris yang dilakukan pakar yang ahli bukan saja dalam penulisan bahasa Inggris, tetapi juga memahami bidang keilmuan tersebut dan terminologinya.
DEDDY MULYANA. GURU BESAR FIKOM UNIVERSITAS PADJADJARAN
————————
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 21 Februari 2017, di halaman 7 dengan judul “Hantu “Scopus””.