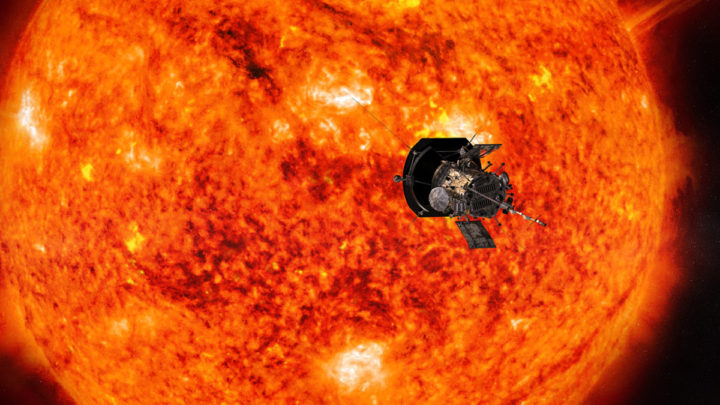Mereka menyebut kami anak-anak sinar.
Di sekolah, kulit kami selalu paling mencolok—hijau muda, berpendar tipis ketika matahari sore menyinari ruang kelas. Guru-guru berhenti memberi kami jatah makan siang karena kami tak membutuhkannya. Kami duduk diam saat teman-teman lain membuka kotak bekal, mencium aroma nasi goreng, atau sup panas yang mengepul. Aku hanya memandangi mereka, tanpa rasa iri, tanpa rasa ingin. Setiap kali mereka tertawa, membicarakan rasa favorit, aku hanya bisa menatap ke luar jendela, mencari makna di antara sinar yang membelai pipiku.
Aku Alya. Usia enam belas. Generasi pertama manusia fotosintetik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kau tidak pernah lapar?” tanya Rehan suatu siang, matanya penuh rasa ingin tahu. Ia menyodorkan sepotong roti.
Aku menggeleng. “Tubuhku cukup dengan sinar.”
“Tapi kau tak penasaran rasanya?”
Aku mengerutkan kening. Rasa? Bagiku rasa hanyalah konsep yang dijelaskan ibu dalam buku pelajaran sejarah. Dulu manusia makan, kata ibu. Dulu manusia berburu, memasak, merasakan nikmat atau getir. Kami tidak. Kami sudah disempurnakan. Setidaknya itulah yang selalu mereka katakan.
Namun dalam keheningan malam, ketika semua orang tidur, aku sering mengelus perutku sendiri. Bukan karena lapar—karena aku tak tahu apa itu lapar—tapi karena ingin tahu: apakah di dalam sana ada ruang untuk sesuatu yang lain?
Ibuku, Dr. Kenanga, adalah salah satu perancang genetik proyek ini. Ia sering memandangi kulitku di bawah mikroskop rumah. “Kloroplasmu sehat,” katanya bangga. “Kau masa depan, Alya. Kau tak akan pernah kelaparan, tak akan pernah kelelahan.”
“Masa depan?” tanyaku sekali waktu, duduk di kursi perawatan.
“Ya. Manusia baru. Bebas dari kebutuhan-kebutuhan primitif.”
Aku tersenyum seperti anak baik. Tapi di dalam, aku sering bertanya-tanya: jika aku masa depan, mengapa aku merasa kosong?
Di sekolah, anak-anak sinar seperti aku dipisahkan. Kami punya ruang khusus, kursi yang dilengkapi lampu UV kecil untuk memastikan suplai energi. Kami diajari menghitung, membaca, memproses data. Semua yang rasional. Tidak ada kelas seni atau olahraga. Mereka bilang itu tak penting. Kami tidak perlu membuang energi untuk hal tak berguna.
Tapi setiap kali aku melintasi ruang seni, aku mendengar suara Rehan memetik gitar. Suaranya seperti sesuatu yang menembus lapisan sinar dan data yang memenuhi hidupku. Aku berdiri di ambang pintu, diam-diam mendengarkan. Suatu hari ia memergoki aku.
“Kau suka musik?” tanyanya.
“Aku tidak tahu,” jawabku jujur. “Aku hanya… merasa sesuatu.”
“Apa?”
Aku diam. Aku tidak punya kata untuk menjelaskannya.
Malam-malam panjang kulalui dengan memandangi langit dari balkon apartemen. Kota futuristis ini penuh menara surya, lampu-lampu matahari buatan yang menyinari kami 24 jam. Manusia biasa makan di kafe dan restoran, tertawa, bersuara riuh. Kami, anak-anak sinar, duduk di taman kota, memejamkan mata, memanen energi. Diam. Sunyi. Nyaris tanpa emosi.
“Kenapa mereka tertawa, Bu?” tanyaku suatu malam.
“Karena mereka perlu menghibur diri dari rasa lelah,” jawab Ibu tanpa menoleh dari laptopnya.
“Apakah mereka lebih bahagia dari kita?”
Ibu terdiam lama. “Bahagia itu relatif, Alya. Kau tidak perlu memikirkan itu. Kau berbeda.”
Hingga hari itu tiba. Badai matahari datang tanpa peringatan. Suplai energi kota lumpuh. Panel surya mati. Lampu matahari buatan padam. Selama dua hari penuh, langit tertutup debu kosmik. Kami, anak-anak sinar, mulai melemah. Kloroplas kami berteriak diam-diam, mencari cahaya yang tak ada. Tubuh-tubuh hijau pucat tumbang di jalan, napas dangkal, kulit mulai memucat keabu-abuan.
Aku terbaring di ruang perawatan, cahaya emergency redup. Nafasku dangkal. Ibuku panik, wajahnya pucat.
“Alya, dengarkan Ibu,” katanya, menggenggam tanganku. “Ini mungkin terasa aneh, tapi kau harus makan.”
“Aku… tidak tahu caranya,” bisikku. Suaraku patah-patah, seperti radio tua.
“Rehan!” teriak Ibu pada pemuda yang berdiri di sudut. Ia sudah berhari-hari berjaga di sana, menolak pulang meski dilarang petugas.
Rehan mendekat dengan mangkuk bubur hangat. Uapnya naik ke wajahku, aroma asin dan gurih menusuk indra yang selama ini tidur.
“Alya, coba. Untukku,” ucapnya pelan, matanya berkaca-kaca.
Aku menutup mata. Suapan pertama menyentuh lidahku seperti ledakan kecil: rasa, tekstur, panas, hidup. Tubuhku menggigil. Mata ibu basah. Rehan tersenyum dengan lega.
Dan tiba-tiba… perutku bergejolak. Ada rasa lapar yang tak pernah kukenal sebelumnya, memaksa diriku membuka mulut lagi. Suapan kedua, ketiga, keempat. Aku menangis sambil makan. Aku baru tahu bahwa hidup tak hanya sinar. Hidup juga rasa. Sakit. Kenyang. Syukur.
Hari-hari setelah badai adalah hari-hari baru. Kota memulihkan diri. Lampu-lampu menyala kembali. Anak-anak sinar dipulihkan secara medis. Tapi di dalam diriku sudah ada sesuatu yang berbeda. Aku mencari rasa. Aku minta Ibu mengajariku makan makanan lain: roti, sup, buah. Setiap rasa membangunkan emosi yang selama ini terkubur. Aku tertawa pertama kali karena pedasnya cabai. Aku menangis karena pahitnya sayur pare.
Tapi pemerintah tidak senang. “Proyek fotosintesis harus tetap murni,” kata seorang pejabat saat Ibu dipanggil ke kantor pusat. “Kita tidak boleh mencampur sifat lama dengan yang baru.”
“Tapi mereka manusia, bukan mesin!” seru Ibu, membela.
“Manusia yang sudah ditingkatkan tidak boleh mundur ke belakang. Itu pemborosan sumber daya.”
Ibu pulang dengan wajah hancur. “Alya, mereka ingin memisahkanmu dari teman-teman manusia biasa. Mereka ingin kau dipindahkan ke fasilitas khusus.”
“Tidak!” suaraku pecah. “Aku ingin tetap di sini. Aku ingin tetap dengan Rehan. Aku ingin… hidup!”
Ibu menatapku, kaget mendengar nada emosiku yang baru. “Kau sudah berubah…”
“Aku manusia, Bu. Lebih manusia daripada sebelumnya.”
Malam itu aku pergi ke taman kota. Anak-anak sinar lain duduk memejamkan mata, memanen cahaya dari lampu baru. Mereka tenang, tapi hampa. Aku berjalan melewati mereka, menuju panggung kecil tempat musisi jalanan bermain. Rehan ada di sana, memetik gitar. Aku duduk di depannya, mendengarkan. Lagu-lagunya kini mengalir masuk ke dalam diriku, membangunkan hal-hal yang tak pernah kutahu ada.
“Aku takut, Rehan,” kataku pelan saat lagu selesai.
“Takut apa?”
“Takut mereka memaksaku kembali menjadi seperti dulu.”
Rehan menggenggam tanganku. “Kau sudah membuka matamu. Tak ada yang bisa menutupnya lagi.”
Aku menatap tangannya yang hangat, kontras dengan kulit hijauku. “Kalau aku harus melawan?”
“Aku di sini,” katanya. “Selalu.”
Beberapa minggu kemudian, pemerintah memanggil Ibu lagi. Mereka memutuskan memindahkan semua anak sinar ke fasilitas isolasi, dengan alasan penelitian lanjutan. Malam itu Ibu memelukku erat.
“Aku tak bisa melawan mereka, Alya. Tapi kau bisa. Kau harus menunjukkan pada dunia bahwa kau bisa menjadi lebih dari sekadar anak sinar.”
Aku menangis. Untuk pertama kalinya, aku menangis bukan karena rasa sakit fisik, tapi karena takut kehilangan.
Esoknya, di depan gedung pemerintahan, aku berdiri di atas mimbar. Ratusan kamera memantau. Ribuan orang berkumpul. Aku menarik napas panjang.
“Kami diciptakan untuk bertahan,” suaraku menggaung. “Tapi bertahan bukan berarti melupakan apa yang membuat kita manusia. Kami bukan hanya sel kloroplas yang memanen sinar. Kami punya hati, punya rasa, punya pilihan. Kami memilih untuk tetap merasakan.”
Orang-orang mulai berbisik. Beberapa pejabat marah. Tapi banyak yang bertepuk tangan. Rehan berdiri di antara kerumunan, senyumnya memberiku kekuatan.
“Mungkin masa depan bukan hanya tentang meninggalkan lapar,” lanjutku, “tapi juga merangkul rasa. Dan kami akan memperjuangkannya.”
Aku menutup pidato dengan air mata mengalir. Untuk pertama kalinya, aku merasa hidup sepenuhnya. Matahari sore menyinari wajahku, kloroplasku berpendar, tapi perutku pun penuh dengan rasa baru. Dan di tengah lautan manusia itu, aku tahu satu hal: evolusi sejati bukanlah menghapus masa lalu, melainkan menulis ulangnya dengan keberanian.
tepian Kali Cikumpa, Depok, pertengahan Juli 2025 yang basah
Cerpen: Avicenia