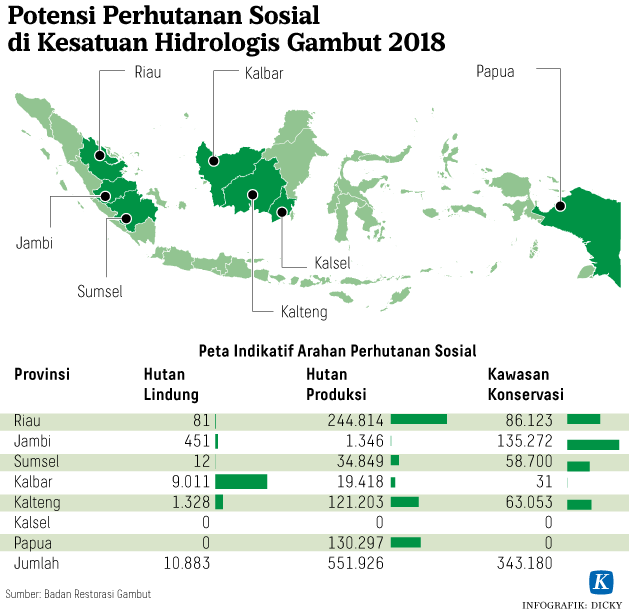Perhutanan sosial menjadi program manis yang ditawarkan dan dijalankan Presiden Joko Widodo.. Namun, proses menuju keadilan akses warga dalam pengelolaan kawasan hutan terancam terhenti.
KOMPAS/VINA OKTAVIA–Petani hutan melintasi jembatan rusak di dalam kawasan Hutan Lindung Batu Tegi, Tanggamus, Rabu (19/2/2020).
Perhutanan sosial menjadi program manis yang ditawarkan dan dikerjakan Presiden Joko Widodo sejak periode pertama memimpin Indonesia. Janji dalam Nawa Cita untuk memberikan ruang kelola kawasan hutan seluas 12,7 juta hektar menjadi harapan baru masyarakat yang mengharapkan keadilan ekonomi berupa terurainya ketimpangan pengelolaan hutan bisa terwujud.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Meski angka tersebut sebenarnya kurang ambisius mengingat masih terdapat hampir 90 juta hektar (ha) kawasan hutan berstatus hutan produksi, hutan lindung, dan hutan produksi terbatas, yang bisa dimanfaatkan dalam berbagai skema perhutanan sosial. Angka ini belum termasuk sebagian wilayah pada hutan konservasi yang juga bisa dimanfaatkan masyarakat dalam zona pemanfaatan melalui kemitraan konservasi.
Namun sebagai pembuka untuk mengatasi ketimpangan, program tersebut disambut dengan positif. Harapannya, suatu saat peran kelola masyarakat bisa membalikkan angka lebih dari 90 persen pengelolaan hutan produksi oleh korporasi. Bila angan-angan tersebut terjadi, proyeksinya bisa tercapai pemerataan ekonomi karena kue hutan tak lagi dinikmati sekelompok elit pemodal besar tetapi juga masyarakat di sekitar hutan.
Target 12,7 juta ha yang sempat “direvisi” menjadi 4,38 juta ha pada awal Maret 2018 tersebut kini tercapai 4,07 juta hektar (data Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial per 9 Maret 2020). Ini dengan catatan untuk hutan adat baru berupa penetapan seluas 44.682,34 ha dan penunjukan 914.927,13 Ha. Dengan kata lain, di luar hutan adat, capaian target mencapai 3,1 juta ha.
Selama periode 2015-2019, terjadi kenaikan hampir 7 kali lipat (tanpa hutan adat) pemberian luas ruang kelola kawasan hutan bagi masyarakat dibandingkan luasan izin hutan bagi masyarakat yang ditinggalkan periode pemerintahan sebelumnya. Dalam berbagai kesempatan, pemerintah menyatakan target 12,7 juta ha dalam Nawa Cita pertama tersebut dilanjutkan ke dalam pemerintahan kedua Presiden Joko Widodo yang kini bersama Wakil Presiden Ma’ruf Amin.
Keadilan akses terancam
Namun, perkembangan menuju keadilan akses terhadap sumber daya alam – dalam hal ini hutan – bagi masyarakat ini kini terancam mandek, bahkan hilang. Menurut dosen Departemen Hukum Lingkungan pada Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Totok Dwi Diantoro, draf Rancangan Undang Undang (RUU) Cipta Kerja terkait Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, menghapus pasal 27-29 yang mengatur pemberian izin bagi perorangan dan kelompok masyarakat.
“Saya meyakini dengan dihapusnya pasal-pasal yang memberi pengakuan obyek hukum masyarakat sebagai pengelola konsesi, meski tidak disebut konsesi perhutanan sosial, maka peluang masyarakat itu menjadi tidak ada,” ungkapnya.
Hal itu berarti keberpihakan pada masyarakat sekitar hutan tidak ditunjukkan dalam RUU Cipta Kerja. Peluang masyarakat perseorangan maupun kelompok masyarakat atau koperasi untuk secara mandiri mengelola dan menikmati hasil dari sumber daya hutan menjadi kecil.
KOMPAS/VINA OKTAVIA–Ketua Gabungan Kelompok Tani Mandiri Lestari, KPH Batu Tegi Kabupaten Tanggamus, Lampung, Eko P. Juliana menanam pohon di lahan kritis di dalam kawasan Hutan Lindung Batu Tegi, Tanggamus, Rabu (19/2/2020).
Adapun RUU Cipta Kerja hanya memberikan izin kepada perusahaan, entah berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau swasta. Peluang masyarakat hanya ada pada pasal yang menyebut pemegang izin usaha kehutanan bisa bekerja sama dengan koperasi dan Badan Usaha Milik Desa. Hal itu mereduksi semangat untuk memberikan akses lebih luas bagi keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan.
Dalam buku Status Hutan dan Kehutanan Indonesia (SOIFO) 2018 yang diterbitkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyebutkan terdapat 25.863 desa yang berada di dalam dan sekitar area hutan di Indonesia. Sebagian dari desa-desa yang dihuni masyarakat lokal dan masyarakat adat juga penduduk pendatang dan transmigran masuk kategori miskin.
Upaya perhutanan sosial – di luar pencapaian dan keberhasilan masyarakat berhasil memanfaatkan izin-izin tersebut bagi kesejahteraannya – merupakan terobosan dan harapan bagi warga untuk mentas dari kemiskinan dengan cara legal. Selain itu, keberadaan mereka yang berada di sekitar kawasan hutan pun menjadi sumber daya yang mengatasi keterbatasan dalam pengawasan hutan.
Selain menghilangkan harapan masyarakat sekitar hutan, RUU Cipta Kerja pun membangkitkan kembali ruang kriminalisasi masyarakat yang telah ‘dianulir’ Mahkamah Konstitusi. Bahkan, RUU Cipta Kerja memberikan sanksi lebih berat.
KOMPAS/WAWAN H PRABOWO–SK Perhutanan Sosial – Warga memilih bibit tanaman produktif usai menerima Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo di Taman Hutan Pinus Kenali, Jambi, Minggu (16/12/2018). Dalam kesempatan itu, Presiden menyerahkan 92 unit SK Pehutanan Sosial seluas 91 hektare kepada 8.165 kepala keluarga (KK). Izin pengelolaan lahan dalam Perhutanan Sosial tersebut diberikan selama 35 tahun.
Pada UU Kehutanan, sanksi menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang diancam penjara maksimal 10 tahun dan denda maksimal Rp 5 miliar. Pada RUU Cipta Kerja, sanksinya menjadi paling singkat 10 tahun dan denda maksimal Rp 7,5 miliar.
Padahal putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95 Tahun 2014, dalam pertimbangan hukumnya menyatakan tindak pidana kehutanan itu tidak berlaku bagi masyarakat yang hidup secara turun-temurun di dalam hutan. Ini sepanjang menebang pohon, memanen, memunguthasil hutan, dan beternak dalam kawasan hutan bukan untuk kepentingan komersial.
Mahkamah Konstitusi berpendapat, masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan membutuhkan sandang, pangan, dan papan untuk kebutuhan sehari-harinya yang harus dilindungi oleh negara, bukan malah diancam dengan hukuman pidana.
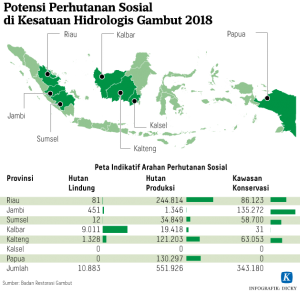 “Pasal berlapis” pun menanti masyarakat berkat ancaman pada UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) yang dimodifikasi RUU Cipta Kerja.
“Pasal berlapis” pun menanti masyarakat berkat ancaman pada UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) yang dimodifikasi RUU Cipta Kerja.
Rancangan UU menerapkan sanksi administrasi minimal Rp 500.000 dan paling banyak Rp 500 juta yang apabila tak sanggup memenuhinya, selanjutnya diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 bulan dan paling lama 2 tahun. “Meski dengan ancaman yang berbeda, lebih rendah, tapi mengancam satu perbuatan yang sama,” kata Totok.
Tanpa RUU Cipta Kerja saja, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mencatat sedikitnya terjadi 25 kasus kriminalisasi masyarakat adat yang menjerat 33 orang. Mereka mengalami diskriminasi berupa fisik dan non fisik, akses ke hutan terbatas, pengusiran dan lain-lain dengan menggunakan UU P3H.
Sejumlah pasal dalam RUU Cipta Kerja pun dikhawatirkan menambah marak konflik agraria, dalam hal ini di sektor kehutanan, padahal kasus yang ada saja sulit diselesaikan. Konsorsium Pembaruan Agraria, dalam catatan akhir tahun 2019, mengungkapkan terdapat 20 konflik agraria di sektor kehutanan dari total 279 konflik.
Meski dari jumlah konflik agrarian menempati urutan kelima setelah perkebunan, infrastruktur, properti, dan pertambangan; sektor kehutanan memiliki luasan konflik yang terluas yaitu 274.317,3 ha dari total luas konflik 734.239,3 ha.
KOMPAS/VINA OKTAVIA–Warga yang mengelola kawasan hutan lindung memindahkan bibit tanaman kakao yang akan ditanam di dalam hutan, Sabtu (13/4/2019). Melalui skema perhutanan sosial, sebanyak 171 petani hutan mendapat izin pengelolaan hutan melalui wadah Gabungan Kelompok Tani Hutan Lestari.
Sejumlah “terobosan” untuk mempercepat kepastian berusaha dilakukan dengan menghapus penjelasan yang menguraikan mengenai etail pengukuhan kawasan, khususnya tahapan penunjukan. Pada tahapan ini, UU No 41 mengamanatkan agar dilakukan pengumuman rencana batas kawasan hutan terutama pada lokasi yang berbatasan dengan tanah hak.
Kondisi tersebut akan memperuncing tumpang tindih penguasaan tanah hak dan penunjukan kawasan hutan yang pada ujungnya menciptakan konflik yang tak menguntungkan pihak manapun, termasuk pemohon izin dan masyarakat.
Sudah saatnya, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang seorang rimbawan mengingat kembali penekanannya yang tertulis dalam SOIFO (2018), mengenai perlunya corrective action atau langkah perbaikan dalam perancangan tata kelola hutan Indonesia, yaitu saatnya hutan harus menyejahterakan rakyat. Jangan sampai kembali ke masa lalu di tahun 1990-an di mana masyarakat sekitar kawasan hutan kembali hanya sebagai penonton, bahkan nelangsa, meski dekat dengan sumber kehidupannya, hutan.
Oleh ICHWAN SUSANTO
Editor: EVY RACHMAWATI
Sumber: Kompas, 29 April 2020