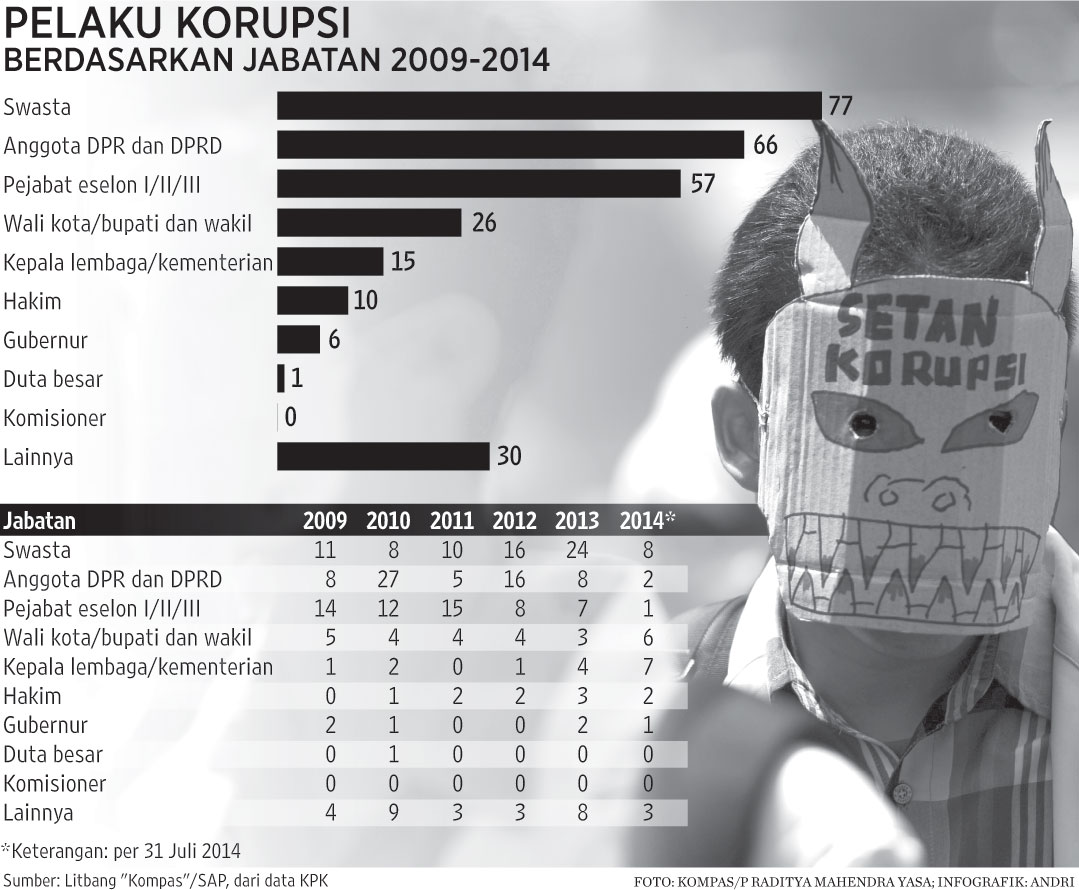Meski telah berulang kali pejabat negara tertangkap tangan dan dijebloskan ke penjara gara-gara korupsi, suap, ataupun pemerasan, penyelenggara negara lain tak juga jera. Jumlah pejabat di berbagai tingkatan yang tersandung kasus penyalahgunaan kekuasaan terus bertambah setiap hari. Apakah kekuasaan sedemikian melenakan hingga mereka terjebak dalam kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme?
Kasus terakhir pejabat negara yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik. Ia menjadi menteri ketiga di antara 34 menteri dalam Kabinet Indonesia Bersatu II yang ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai tersangka.
Hasrat untuk menyalahgunakan kekuasaan, termasuk korupsi, tak identik dengan jabatan. Sejarawan Inggris, Lord Acton, pada abad ke-19 pernah menyebut, ”Power tends to corrupt. Absolute power corrupts absolutely” (Kekuasaan cenderung korup. Kekuasaan mutlak pasti korup). Namun, riset psikologi membuktikan, kondisi itu hanya berlaku bagi pemegang kuasa yang mementingkan ego pribadi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Asisten Profesor Psikologi di Universitas Illinois, Urbana- Champaign, Amerika Serikat, Michael W Kraus dalam Three Myths About Power, Power Corrupts? Not Always di psychologytoday.com, 23 Oktober 2011, menilai pernyataan Acton itu hanya mitos.
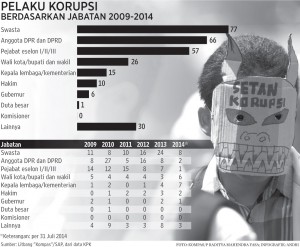 Mengutip riset Serena Chen yang dipublikasikan di Journal of Personality and Social Psychology, 2001, tentang hubungan antara kuasa dan tanggung jawab sosial, Michael menulis individu pemegang kuasa yang mementingkan egonya tak akan membantu rekannya meski telah ditugasi membantu. Sebaliknya, mereka yang melepaskan egonya atas kekuasaan, tetap membantu temannya.
Mengutip riset Serena Chen yang dipublikasikan di Journal of Personality and Social Psychology, 2001, tentang hubungan antara kuasa dan tanggung jawab sosial, Michael menulis individu pemegang kuasa yang mementingkan egonya tak akan membantu rekannya meski telah ditugasi membantu. Sebaliknya, mereka yang melepaskan egonya atas kekuasaan, tetap membantu temannya.
Itu berarti, kekuasaan tak selalu mendorong orang untuk menyalahgunakan kuasanya, bergantung pada motif dan ego setiap individu.
Meski demikian, pernyataan Acton itu ada benarnya. Penelitian psikolog Philip G Zimbardo tentang Stanford Prison Experiment, 1971, menunjukkan, seseorang yang diberi kekuasaan cenderung menyalahgunakan kuasanya. Kondisi itu sesuai dengan pernyataan presiden ke-16 AS, Abraham Lincoln (1861-1865), bahwa ”Hampir semua orang bisa tahan terhadap kesengsaraan. Namun, jika kamu ingin menguji karakter seseorang, berilah dia kekuasaan.”
Kendali diri
Potensi penyalahgunaan kekuasaan yang bergantung pada karakter pemegang kekuasaan juga diungkapkan ahli psikologi politik dan kekuasaan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, Bagus Riyono, Minggu (7/9). ”Terjadi korupsi atau tidak itu tergantung ada peluang dan pandangan setiap individu tentang untung-rugi,” katanya.
Jabatan dianggap sebagai peluang memperkaya diri. Itu membuat sumpah jabatan, dosa, dan Tuhan tak lagi jadi penjaga mereka untuk melaksanakan amanat. Materi pun jadi pandangan hidup.
Cara berpikir pun jadi pendek dan nurani tumpul. Untung-rugi adalah pertimbangan utama dalam melakukan setiap tindakan, termasuk menghitung berapa uang yang bisa didapat dari korupsi dibandingkan besarnya hukuman penjara dan denda yang kadang tak seberapa. Belum lagi kemungkinan bisa membeli fasilitas di penjara, ada potongan hukuman, hingga peluang minta pembebasan bersyarat seusai menjalani 2/3 masa hukuman.
Meski demikian, Bagus menilai penyalahgunaan kekuasaan dan pandangan hidup materialis bukan budaya Indonesia. Kondisi itu umum terjadi di semua budaya, pada orang yang mudah terbuai kuasa. ”Karakter itu jadi menonjol di Indonesia karena hukum belum kuat,” katanya.
Kepala Pusat Studi Otak dan Perilaku Sosial Universitas Sam Ratulangi (Unsrat), Manado, yang juga dosen neuroanatomi Fakultas Kedokteran Unsrat, Taufiq Pasiak, mengatakan, banyaknya penyelenggara negara menyalahgunakan kekuasaan menunjukkan lemahnya sistem kendali diri di otak mereka.
Sistem kendali diri dibentuk sistem pengimbalan (reward) yang memotivasi melakukan sesuatu dan hilangnya sistem kasih (lose affection) yang membuat seseorang tak mau rugi. Ketika muncul peluang, terlebih saat ada tekanan, mereka yang tak punya sistem kendali diri memadai mudah terjatuh dalam penyelewengan kekuasaan.
”Ini persoalan besar bangsa Indonesia yang tak cukup diajar untuk memiliki sistem kendali diri yang baik,” ujarnya.
Buruknya sistem kendali diri juga membuat koruptor terjebak dalam keserakahan. Mereka terus menuruti pikiran bawah sadar yang menuntut meraih semua peluang dan menimbun segala sumber daya yang bisa diraih dari peluang itu meski sudah berlebih memilikinya.
Sialnya, lanjut Taufiq, keserakahan dan penimbunan sumber daya itu disuburkan oleh lingkungan. Mulai dari pimpinan, anak buah, orangtua, hingga tokoh agama atau penasihat spiritual penyelenggara negara pun menimbun sumber daya hingga terjadi penimbunan kolegial.
Rekayasa sosial
Sistem kendali diri bisa dibangun karena otak bersifat plastis, mudah berubah jika ada rangsangan dari lingkungan. Karena itu, rekayasa sosial untuk mematangkan sistem kendali diri harus dilakukan.
Dalam pendidikan, pematangan bisa dilakukan dengan memperhatikan setiap murid sebagai individu unik, tak disamakan. Namun, kemampuan itu jarang dimiliki guru karena banyaknya murid yang harus diperhatikan hingga data psikografis siswa tak terekam. Padahal, rekaman data psikografis itu bisa jadi pertimbangan psikologis untuk menilai layak tidaknya seseorang diberi kuasa berdasarkan kondisi mentalnya.
Pendidikan agama juga perlu diformulasi ulang. Taufiq menilai pendidikan agama selama ini lebih menekankan pada pengajaran dogma untuk memperkuat keimanan dan kurang memperhatikan pendidikan akhlak atau budi pekerti. Kalaupun ada, pendidikan pekerti sulit diterapkan siswa dengan praktis.
Oleh: M Zaid Wahyudi
Sumber: Kompas, 10 September 2014