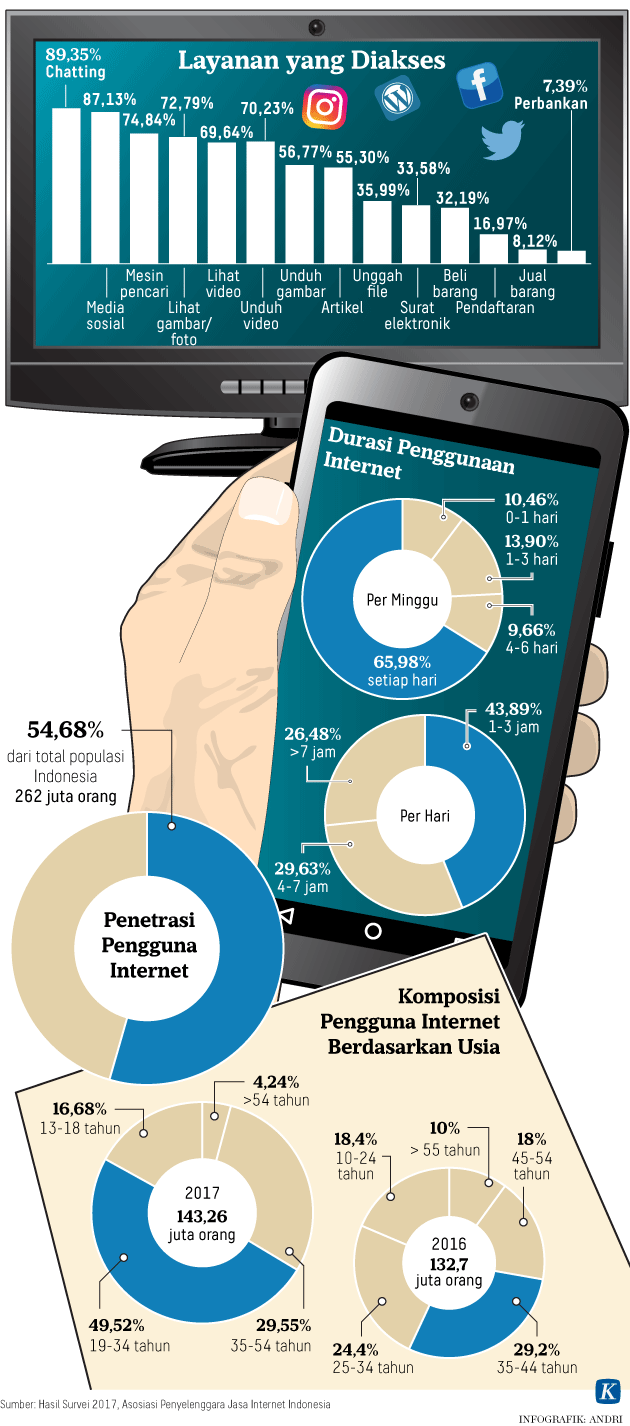Sudah lima tahun, David Mario (25), pegawai swasta di Jakarta mencandu Instagram. Hampir tiap jam, ia membuka media sosial yang digemarinya itu. Saat makan, di kendaraan umum, menonton televisi, sebelum tidur, hingga saat buang hajat, jemarinya tak lepas dari layar telepon seluler.
”Sebelum tidur, saya bisa mengakses Instagram mulai dari 30 menit sampai 1 jam,” kata David, Sabtu (2/6/2018). Di antara berbagai media sosial, David merasa lebih mencandu Instagram karena media sosial itu memang lebih banyak digunakan teman atau generasi milenial lain serta memiliki banyak fitur menarik.
David menyadari kecanduannya itu selama tiga tahun terakhir. Tak hanya ingin selalu melihat foto orang lain, ia juga terpacu menampilkan foto-foto dirinya yang paling menarik, tak kalah dengan milik orang lain.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
”Rasanya seperti ada yang kurang jika belum mem-posting sesuatu,” katanya.
Sadar dirinya sudah kecanduan, David pun mencoba ’puasa’ Instagram sejak dua minggu terakhir. Usaha itu dilakukan dengan mengubah kebiasaan membuka Instagram dengan mengunduh aplikasi portal berita dan Wattpad sehingga lebih bisa banyak membaca tulisan-tulisan yang lebih berbobot.
KOMPAS/AGUS SUSANTO (AGS)–Anak-anak bermain gawai di Skouw, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Papua, Sabtu (15/7/2017).
”Awalnya, ’puasa’ media sosial itu memang tidak mudah. Namun, situasi itu justru menyadarkan dirinya jika selama ini sudah bergantung pada Instagram,” tambahnya. ”Sekarang lebih terkontrol, paling membuka Instagram hanya saat makan siang,” kata David
Meski baru di tahap awal, usaha membatasi diri mengakses media sosial itu mulai membuahkan hasil. David merasa lebih fokus dan tenang beraktivitas, menambah waktu interaksi dengan teman dan orang sekitar, hingga bisa menghemat pulsa internet yang semula mencapai 1 gigabit sehari menjadi hanya 200 megabit per hari.
Berubah
 Berkembangnya media sosial memang mengubah cara manusia berkomunikasi, dari komunikasi lisan secara langsung menjadi komunikasi melalui berbagai aplikasi percakapan dan media sosial. Perubahan itu memang memudahkan, tapi juga memunculkan banyak masalah baru.
Berkembangnya media sosial memang mengubah cara manusia berkomunikasi, dari komunikasi lisan secara langsung menjadi komunikasi melalui berbagai aplikasi percakapan dan media sosial. Perubahan itu memang memudahkan, tapi juga memunculkan banyak masalah baru.
Dalam komunikasi lisan melalui tatap muka langsung, otak kiri dan kanan manusia akan bekerja bersama. Otak kiri adalah tempat memproses bahasa verbal, baik lisan atau tulisan. Sementara otak kanan tempat memproses bahasa nonverbal, seperti intonasi suara, tatapan mata, mimik muka, hingga gerak tubuh.
”Dalam komunikasi digital, hanya otak kiri manusia yang aktif,” kata Kepala Pusat Neurosains Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka Jakarta Rizki Edmi Edison.
Dalam komunikasi lisan melalui tatap muka langsung, otak kiri dan kanan manusia akan bekerja bersama. Dalam komunikasi digital, hanya otak kiri manusia yang aktif.
Namun, komunikasi langsung lebih mudah menimbulkan kelelahan. Karena dua sisi otak bekerja, otak butuh lebih banyak energi untuk bekerja. Masalahnya, kecenderungan otak bekerja adalah dengan menghindari hal-hal yang melelahkan dan butuh energi banyak.
Akibatnya, manusia cenderung lebih menggemari komunikasi lewat tulisan daripada bertemu langsung. Wajar jika akhirnya banyak orang sangat aktif di media sosial, tetapi justru bungkam saat bertemu langsung.
Di sisi lain, keranjingan komunikasi digital juga bisa memengaruhi kemampuan seseorang berkomunikasi secara lisan. Namun, situasi itu umumnya akan dialami mereka yang sejak kecil kurang dibiasakan atau diajak berkomunikasi langsung.
Kemampuan komunikasi lisan itu sangat dipengaruhi oleh bagaimana anak dibesarkan. ”Jika sejak kecil anak dilatih memaknai bahasa nonverbal dengan baik, kemampuannya berkomunikasi langsung dan berempati akan tetap terjaga meski aktif bermedia sosial,” kata Edmi.
Kebohongan
Penggunaan satu sisi otak dalam komunikasi digital juga membuat berbohong lebih mudah dilakukan dalam komunikasi di dunia maya dibandingkan jika komunikasi secara langsung. Dalam pesan tulisan, orang memang akan lebih sulit menilai bahasa nonverbal yang disampaikan seseorang bersamaan dengan bahasa verbal yang diutarakan.
Penggunaan satu sisi otak dalam komunikasi digital juga membuat berbohong lebih mudah dilakukan dalam komunikasi di dunia maya dibanding jika komunikasi secara langsung.
Kondisi itu juga membuat kebohongan lebih mudah disebarkan dalam komunikasi digital. Di samping itu, karakter media sosial yang memungkinkan penyebaran informasi secara cepat dan masif juga akan membuat kebohongan dan berita bohong lebih mudah menyebar.
Repotnya, meski berita bohong itu sudah diklarifikasi dengan berita yang benar, informasi yang benar tetap sulit menyebar.
Kondisi itu diperparah dengan kecenderungan manusia menilai sebuah informasi yang sering dipengaruhi efek kebenaran ilusi (illusory truth effect). Dalam efek itu, sebuah informasi akan dipercayai kebenarannya jika sesuai logikanya atau pernah mendengar informasi sebelumnya.
Keadaan itu membuat sebuah berita bohong akan lebih mudah dipercayai dibanding informasi yang benar. Selain itu, berita bohong yang diulang terus-menerus, lama-lama akan dianggap sebagai kebenaran.
Kendali diri
Komunikasi melalui media sosial juga cenderung membuat orang hilang kendali. Banyak orang tak sadar kegemarannya bermedia sosial telah menggiring mereka dalam perilaku berbahaya dan merugikan, mulai dari mengakses media sosial sambil berjalan, berkendara, menemani anak belajar, hingga saat makan bersama keluarga.
Kepekaan mereka terhadap bahaya juga mengendur. Akibatnya, banyak orang nekat berswafoto di lokasi-lokasi bencana atau ekstrem demi menghasilkan foto yang unik dan berbeda di antara yang lain.
Candu internet dan media sosial juga membuat banyak orang nekat membeli pulsa meski harus mengorbankan uang makan atau biaya pendidikan. Internet juga membuat orang makin terasing, sibuk dengan diri sendiri meski ada di tengah kerumunan orang,
”Banyak orang belum matang saat menggunakan internet dan media sosial,” kata ahli psikologi siber yang juga Ketua Program Studi Doktor Ilmu Psikologi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Neila Ramdhani.
Penggunaan media sosial juga memengaruhi kesehatan jiwa masyarakat modern. Banyak riset menunjukkan pemakaian media sosial telah meningkatkan stres, kecemasan, hingga depresi. Kondisi itu muncul saat mereka melihat kesenangan dan kebahagiaan orang lain yang ditampilkan dalam foto atau video saat berlibur, makan, atau berbagi hal-hal menyenangkan lain.
Penggunaan media sosial juga memengaruhi kesehatan jiwa masyarakat modern. Banyak riset menunjukkan pemakaian media sosial telah meningkatkan stres, kecemasan, hingga depresi.
Pembandingan sosial itu akan mudah menimbulkan rasa iri, curiga hingga paranoid karena khawatir makin ’kalah’ dibanding orang lain. Tak jarang, tudingan dan fitnah pun muncul hingga menciptakan konflik.
”Kondisi itu akan mengancam kesehatan mental seseorang karena merasa hidupnya lebih menderita dan tak bahagia seperti orang lain,” tambahnya.
Neila menilai pendidikan menjadi kunci untuk membangun kematangan masyarakat menggunakan teknologi, maupun media sosial. Pendidikan itu bukan hanya di sekolah, tetapi juga di rumah melalui keteladanan guru dan orangtua.
Pemerintah pun harus ambil peran, tidak bisa hanya meminta masyarakat bijak menggunakan internet atau mewaspadai hoaks tanpa mengendalikan persaingan harga internet murah yang masif antarberbagai operator telekomunikasi seluler, khususnya untuk mengakses media sosial.
Bagaimanapun, internet sama seperti teknologi lain, selalu memiliki dua sisi, yaitu mendatangkan manfaat atau justru menjerumuskan manusia. Karena itu, masyarakat perlu dipersiapkan menghadapi pemanfaatan internet yang akan makin masif ke depan. Jika tidak, bukan hanya masyarakat yang akan mengalami sakit mental, tetapi bangsa pun bisa ’sakit’ atau tidak berketahanan hingga terpecah belah akibat internet dan media sosial.–M ZAID WAHYUDI/DEONISIA ARLINTA
Sumber: Kompas, 3 Juni 2018