Secara geologi, wilayah Lombok dan Palu memiliki kerawanan bencana yang tinggi. Sayangnya, kondisi rentan bencana tersebut belum diimbangi pengetahuan mitigasi bencana oleh warganya.
KOMPAS/VIDELIS JEMALI–Tampak tenda darurat di kamp pengungsian Kelurahan Balaroa, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Sulteng, Jumat (1/11/2019). Tenda-tenda itu ditempati 200 keluarga penyintas likuefaksi Balaroa yang tak mendapatkan hunian sementara yang bangunannya bercorak semipermanen. Selama 13 bulan mereka menempati tenda tersebut pascagempa lalu.
Tingkat kerawanan gempa yang tinggi di Lombok dan Palu tak dibarengi tingginya upaya mitigasi bencana di daerah itu. Minimnya pengetahuan warga terkait bencana tecermin dari hasil survei Kompas terhadap 200 penyintas bencana pada 22-29 Oktober 2019 di Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, serta Kota Palu dan Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
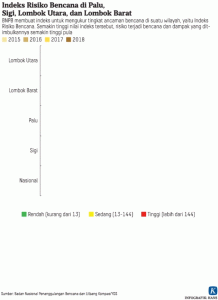 Hampir semua responden, sembilan dari sepuluh, mengaku tak tahu daerah tempat tinggalnya rawan bencana. Selain itu, 61 persen responden belum memahami metode penanganan saat bencana.
Hampir semua responden, sembilan dari sepuluh, mengaku tak tahu daerah tempat tinggalnya rawan bencana. Selain itu, 61 persen responden belum memahami metode penanganan saat bencana.
Rendahnya literasi bencana di Palu dan Lombok diperparah tingginya keinginan pengungsi kembali ke lokasi tempat tinggal sebelumnya. Mayoritas responden (69 persen) mengungkapkan keinginan mereka kembali ke rumah asal. Padahal, mereka mengalami dahsyatnya dampak bencana di tempat tinggal sebelumnya.
Risiko tinggi
Pengetahuan dan kesadaran tentang risiko bencana di suatu daerah menjadi modal dasar mitigasi. Kawasan Lombok, misalnya, dikepung sumber gempa di semua bagian pulau. Di bagian timur dan barat ada Sumbawa Strait Strikeslip Fault sepanjang 270 kilometer. Di bagian utara ada Flores Backarc Thrust dengan panjang lebih dari 1.000 kilometer. Adapun di selatan ada zona subduksi antara lempeng Indo- Australia dan Eurasia.
Wilayah Palu pun tak kalah rawan. Terdapat struktur-struktur geologi teridentifikasi aktif bergerak dan kerap menghasilkan gempa, termasuk sesar Palukoro dengan pergerakan 29 milimeter per tahun.
Tingkat ancaman bencana alam di suatu wilayah diukur Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memakai Indeks Risiko Bencana (IRB) serta ukuran kuantitatif kerugian yang ditimbulkan.
Makin tinggi nilai IRB, kian tinggi pula ancaman bencana dan besarnya kerugian secara fisik hingga ekonomi. Perhitungan kerugian meliputi aspek jumlah penduduk yang terancam, kerusakan bangunan, ekonomi terdampak, dan kerusakan lingkungan.
Sejauh ini, BNPB membagi IRB dalam tiga kelas, yakni tinggi (>144), sedang (13-144), dan rendah (<13). Indeks itu menunjukkan tingkat risiko bencana di Sulteng dan NTB.
Penilaian tingkat risiko di Sulteng mengambil area Kota Palu dan Kabupaten Sigi. Sementara kejadian gempa di Lombok fokus di Lombok Utara dan Lombok Barat.
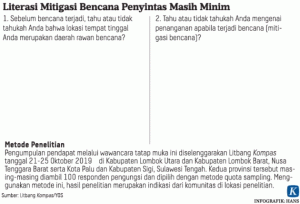 Selama periode 2015-2018, Lombok Barat memiliki nilai IRB tertinggi, yaitu 199. Urutan kedua berada di Kota Palu (171,5) dengan kategori tinggi, dilanjutkan Lombok Utara (140,5) berkategori sedang, dan Kabupaten Sigi (55,75) berkategori sedang. Jika dibandingkan secara nasional, IRB Lombok Barat dan Kota Palu jauh melebihi rata-rata nasional yang memiliki nilai 150,5.
Selama periode 2015-2018, Lombok Barat memiliki nilai IRB tertinggi, yaitu 199. Urutan kedua berada di Kota Palu (171,5) dengan kategori tinggi, dilanjutkan Lombok Utara (140,5) berkategori sedang, dan Kabupaten Sigi (55,75) berkategori sedang. Jika dibandingkan secara nasional, IRB Lombok Barat dan Kota Palu jauh melebihi rata-rata nasional yang memiliki nilai 150,5.
Dengan kondisi wilayah berisiko sedang hingga tinggi, penanganan dan upaya mitigasi bencana di dua provinsi itu harus serius. Jumlah total penduduk terancam bencana di dua provinsi itu 7,8 juta jiwa dan risiko kerusakan lahan karena bencana 4,3 juta hektar.
Kearifan lokal
Melihat rendahnya pengetahuan warga terkait status kebencanaan di Lombok dan Palu, perlu metode tepat membumikan pengetahuan bencana, salah satunya melihat media terbanyak diakses warga.
Hasil survei Kompas pun menunjukkan, ada tiga sumber pengetahuan mitigasi bencana, yakni sosialisasi dari pemerintah (22 persen), media sosial (17,50 persen), dan televisi (11,50 persen).
Pengetahuan sumber informasi itu bisa dipadukan dengan memasukkan kearifan lokal sebagai metode menyebarkan pengetahuan bencana. Contohnya, memasukkan istilah lokal atau menyajikan dalam cerita lokal.
Sejumlah istilah lokal di Palu menunjukkan mitigasi lokal warisan masa lampau. Area Balaroa yang terkena likuefaksi dulu disebut Tagari Lonjo, berarti terbenam dalam lumpur pekat. Demikian pula Petobo yang disebut Biromaru, yaitu rumput di rawa membusuk.
Kondisi lumpur pekat dan rawa menunjukkan material tanah di dua lokasi itu tak terjadi pemadatan dan rawan melunak akibat tekanan air.
Daerah lain, yakni Tondo, yang menjadi lokasi pembangunan hunian tetap bagi korban bencana di Palu, memiliki istilah lokal kaombona atau runtuh. Sementara area Duyu, secara toponimi memiliki arti longsor.
Cerita masa lampau yang disarikan dalam istilah lokal menyimpan pengetahuan mitigasi bencana. Bekal mitigasi lokal itu dilestarikan dengan menuturkan dari generasi ke generasi.
Upaya mitigasi juga bisa didorong lewat penguatan regulasi. Itu bisa dilakukan dengan menentukan zona merah bebas bangunan dan perumusan rencana tata ruang wilayah ke depan. Contohnya, area terdampak bencana di Palu dan sekitarnya jadi zona merah.
Penetapan zona merah perlu dibarengi aturan pelarangan penggunaan area itu untuk ditinggali atau pendirian bangunan. Area itu diutamakan bagi kawasan lindung, ruang terbuka hijau, atau monumen.
Upaya mitigasi bencana di Indonesia mesti berkelanjutan mengingat tren bencana meningkat. Warga perlu diingatkan soal mitigasi bencana, terutama di zona rawan bencana, demi menekan dampak bencana. (LITBANG KOMPAS)–YOESEP BUDIANTO
Sumber: Kompas, 8 November 2019












