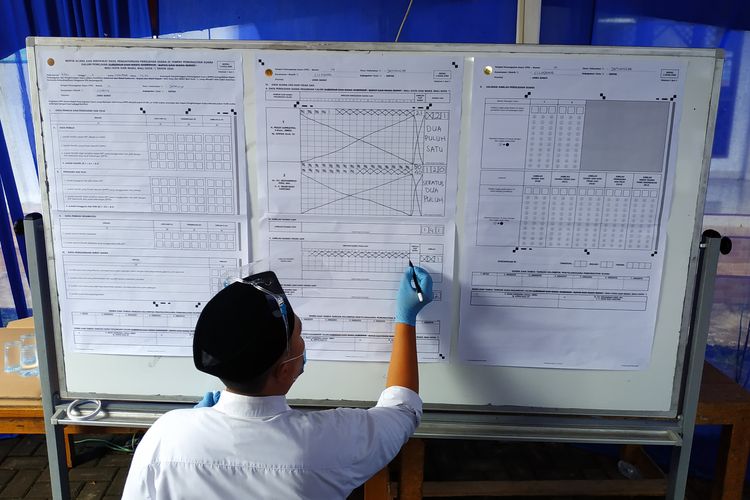MENURUT keputusan terakhir, pemilu akan diadakan awal tahun depan. Terutama pada awal era reformasi ini sebagian masyarakat menganggap sudah tiba waktunya untuk meninjau kembali sistem pemilu yang lama dan menggantinya dengan sistem distrik. Tulisan di bawah ini bermaksud untuk memberi sumbangan pada suatu debat umum mengenai sistem pemilu yang terbaik untuk pemilu yang akan datang. Jika sudah tercapai semacam konsensus umum mengenai hal ini perumusan RUU dapat segera dimulai dan pemilu mungkin dapat dipercepat.
Kritik yang paling keras ter-hadap sistem yang dewasa ini kita pakai adalah bahwa rekrutmen melalui Sistem Daftar memberi peluang untuk koncoisme (cronyism) dan nepotisme, sehingga sebagian anggota DPR dianggap tidak mewakili rakyat dan membawa aspirasinya. Diharapkan sistem distrik dapat mengatasinya karena hubungan antara pemilih dan wakilnya lebih erat.
Mengenai sistem distrik ada persepsi bahwa pelaksanaannya hanya menyangkut masalah bahwa setiap distrik (misalnya kabupaten/Dati II) hanya bisa memajukan satu wakil, sedangkan dalam sistem proporsional suatu daerah pemilihan besar (misalnya propinsi) dapat mengajukan beberapa wakil berdasarkan suatu rumusan tertentu (misalnya satu wakil untuk 400.000 penduduk).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Akan tetapi tidak disadari bahwa ada satu hal yang lebih penting lagi yaitu bahwa pelaksanaan sistem distrik otomatis akan menguntungkan partai besar dan merugikan partai kecil (seperti yang akan saya terangkan di bawah ini). Dan hal ini akan sangat berpengaruh dalam masyarakat kita yang pluralis, dengan banyaknya kelompok minoritas, baik agama, maupun etnis, ditambah dengan kemungkinan munculnya beberapa partai baru.
Membanding sistem proporsional dan sistem distrik
Sistem yang kita pakai selama ini memperlihatkan suatu pola yang oleh masyarakat umum dianggap sudah logis dan wajar, yaitu setiap partai akan memperoleh persentase kursi dalam DPR yang sama dengan persentase suara dalam pemilu (Swedia, Belgia, Belanda). Contoh: partai yang memperoleh 60 persen dari jumlah suara, akan memperoleh 60 persen kursi; partai yang memperoleh 20 persen suara, memperoleh 20 persen kursi. Sistem ini memenuhi rasa keadilan masyarakat karena setiap suara dihitung dan dengan demikian dianggap bersifat representatif sifatnya.
Berbeda sekali dengan sistem distrik. Bisa-bisa suatu partai besar yang memperoleh 60 persen suara akan memenangkan 70 persen kursi. Sebaliknya, dari jumlah suara partai kecil yang memperoleh 25 persen suara bisa saja memperoleh 15 persen kursi (Inggris, Amerika Serikat). Mengapa demikian? Hal ini disebabkan karena sistem distrik selalu mengakibatkan distorsi (distortion effect), yaitu distorsi antara perolehan suara dengan perolehan kursi. Distorsi ini diakibatkan oleh pola khas dari sistem distrik, yaitu perhitungan kursi berdasarkan atas distrik sebagai unit (misalnya Dati II). Setiap distrik berhak atas satu wakil dalam parlemen. Karena satu distrik hanya berhak atas satu wakil, maka calon yang memperoleh suara terbanyak dalam distriknya (misalnya 60 persen), menang. Hal ini dinamakan the first past the post. Suara-suara yang mendukung para calon lain yang kalah (40 persen) tidak dapat membantu partainya di distrik lain dan dianggap hilang (winner takes all). Dan kerugian ini terutama menimpa partai kecil dan karena itu dianggap kurang adil, apalagi jika golongan minoritas terpencar di beberapa Dati II.
Akan tetapi suatu keuntungan dari sistem distrik ialah lebih mudah bagi suatu partai untuk memperoleh mayoritas kursi sehingga tidak perlu mengadakan koalisi.
Sebaliknya, dalam sistem proporsional kesatuan administratif (misalnya propinsi) ditentukan sebagai daerah pemilihan, dan perhitungan suara didasarkan atas propinsi sebagai unit. Dalam batas propinsi itu jumlah suara yang diperoleh oleh setiap partai dari masyarakat menentukan jumlah kursinya di parlemen, artinya persentase perolehan suara setiap partai sama dengan persentase perolehan kursi dalam parlemen.
Akan tetapi sistem ini cenderung mempermudah fragmentasi partai, karena jika timbul konflik dalam suatu partai, anggotanya cenderung memisahkan diri dan mendirikan partai baru dengan perhitungan bahwa ada peluang bagi partai baru itu untuk memperoleh beberapa kursi dalam parlemen melalui pemilu. Jadi, kurang menggalang kekompakan dalam tubuh partai.
Fragmentasi partai banyak terjadi dalam masa Demokrasi Parlementer; kita lihat saja perpecahan di kalangan Masyumi. PSII memisahkan diri dari Masyumi pada tahun 1947, sedangkan NU keluar dari Masyumi pada tahun 1952. Fragmentasi juga dialami oleh PNI pada tahun 1949 waktu Parindra keluar dari PNI; pada tahun 1950 beberapa tokoh keluar dari PNI dan mendirikan PRN. Partai Indonesia Raya (PIR) pada tahun 1954 menjadi dua PIR, satu dipimpin oleh Wongsonegoro, yang lainnya oleh Hazairin. Kejadian-kejadian semacam itu tentu memperlemah kedudukan partai besar dalam DPR Sementara.
Akibatnya, baik Masyumi maupun PNI tidak mempunyai mayoritas yang jelas dan terpaksa harus mengadakan koalisi dengan partai-partai kecil. Ulah partai kecil inilah antara lain yang menimbulkan instabilitas, sehingga perilaku mereka dapat menjatuhkan kabinet. Dengan demikian tiada satu kabinet yang dapat menyusun dan melaksanakan rencana pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Pada Pemilu 1955 lebih dari dua puluh partai mengadu nasibnya.
Bagaimanakah situasi di Indonesia dalam periode Demokrasi Pancasila. Dalam masa akhir-akhir ini Golkar berhasil memperoleh kemenangan yang sangat besar. Menurut saya hal ini disebabkan antara lain karena dua hal, yaitu pertama dilaksanakannya “massa mengambang” yang melarang kegiatan politik di tingkat desa/kecamatan, yang dalam praktek hanya diberlakukan terhadap dua orsospol kecil. Sebab kedua ialah intervensi berlebih-lebihan dari aparatur negara, yang antara lain diwajibkan untuk mencapai “target” tertentu.
Pemilu masa reformasi
Dengan berakhirnya rezim Soeharto, peta politik akan banyak berubah. Sistem tiga partai hampir dapat dipastikan akan diganti dengan sistem multipartai. Banyak partai kecil baru akan muncul, sedangkan beberapa partai lama, yang sejak 1973 sedikit banyak dipaksa untuk bergabung dengan partai lain menjadi tiga orsospol, mungkin akan dihidupkan kembali. Kecenderungan ini dapat mengakibatkan perpecahan dalam tiga partai yang ada sekarang, dan mungkin akan menambah jumlah partai yang bersaing.
Jika kita ingin menyehatkan kehidupan politik kita, ada baiknya kita belajar dari sejarah, dan menghindari meningkatnya kekuatan-kekuatan sentrifugal dalam kepolitikan Indonesia. Untuk itu perlu dicari suatu cara untuk membatasi jumlah partai. Hal itu dapat dilakukan sebelum pemilu misalnya dengan menentukan beberapa syarat. Pembatasan ini juga dapat dilakukan sesudah pemilu, misalnya dengan persyaratan bahwa partai yang memperoleh suara kurang dari persentase tertentu (misalnya 5 persen atau 10 persen) tidak diberi kursi dalam DPR, sekalipun di luar DPR partai itu dapat eksis terus. (Hal ini terjadi di Jerman).
Seandainya ada sepuluh partai yang ikut pemilu, maka persaingan akan sangat seru, mengingat terbatasnya kursi yang diperebutkan (500 kursi). Akan tetapi, dengan sistem proporsional partai kecil masih akan mendapat peluang untuk masuk dalam DPR, sedangkan dengan sistem distrik ada kemungkinan bahwa di antaranya ada yang terpuruk, sebab memang sistem distrik “bias” terhadap partai kecil.
Suatu akibat lain ialah bahwa dengan hadirnya sepuluh partai, akan sukar memperoleh mayoritas yang diperlukan (50 persen + 1), sehingga harus mengadakan koalisi dengan partai lain. Akan tetapi hal ini tidak akan terlalu mengganggu, karena DPR dan Pemerintah tidak boleh saling menjatuhkan dan koalisi secara teoretis dapat bertahan selama lima tahun.
Salah satu kelemahan lain dari sistem proporsional ialah memberikan kedudukan yang kuat pada pimpinan partai melalui Sistem Daftar, karena pimpinan partai menentukan daftar calon akhir. Hal itu memberi peluang untuk nepotisme dan koncoisme (cronyism). Lagi pula, wakil yang terpilih kemungkinan renggang ikatannya dengan warga yang telah memilihnya. Pertama, karena wilayahnya lebih besar (bisa sebesar propinsi), sehingga sukar untuk dikenal banyak orang. Kedua, karena dalam memperoleh mayoritas yang diperlukan (50 persen + 1), sehingga harus mengadakan koalisi dengan partai lain. Akan tetapi hal ini tidak akan terlalu menganggu, karena DPR dan Pemerintah tidak boleh pemilihan semacam ini pengaruh pengurus partai sangat menonjol, sehingga si wakil akan lebih terdorong untuk memperhatikan kepentingan partai, ketimbang kepentingan distriknya.
Untuk masa mendatang mungkin partai-partai sendiri akan lebih terdorong untuk menyusun daftar calon dengan orang yang betul-betul menguasai masalah-masalah dari daerah yang diwakilinya dan memperjuangkan kepentingannya di DPR. Dengan demikian dominasi pimpinan partai dapat dikurangi dan salah satu kelemahan dari sistem proporsional dapat teratasi.
Dalam masalah seperti ini sistem distrik lebih baik, karena wakil dipilih dalam distrik yang jauh lebih kecil dari propinsi dan karena itu hubungan antara wakil dan pemilih lebih erat. Lagi pula, dengan sistem distrik partai-partai kecil akan cenderung untuk dalam satu kabupaten bergabung dengan partai lain untuk memperoleh satu kursi melalui aliansi atau stembusaccoord (kerja sama sebelum pemilu). Hanya dapat dipertanyakan seberapa kuat kerja sama ini dalam masa berikutnya. Selain dari itu perlu dicatat bahwa di beberapa negara sistem ini ternyata telah memberi peluang untuk money politics atau pembelian suara.
Lepas dari analisis di atas, jika kita ingin mengubah sistem pemilu dalam beberapa bulan ini, maka banyak masalah yang harus diatur. Misalnya, jika Dati II dianggap sebagai distrik, maka persoalannya ialah bahwa hanya ada 304 Dati II. Bagaimana dengan seratus lebih kursi lainnya?
Seandainya akan diadakan pembagian distrik baru yang tidak berdasarkan pembagian administratif yang sekarang berlaku, maka perlu peta diatur sedemikian rupa sehingga semua distrik kira-kira sama jumlah penduduknya. Mungkin di Jawa akan lebih banyak distrik dari di luar Jawa, sehingga menguntungkan penduduk di Jawa. Mungkin juga akan timbul kecenderungan bagi partai yang sedang berkuasa untuk menyusun distrik di tempat-tempat di mana dia kuat, agar dapat dimenangkannya. Ini kadang-kadang disebut gerrymandering.
Akhirnya dapat disimpulkan bahwa, seandainya sistem pemilu diganti dengan sistem distrik, maka masyarakat luas harus dalam masa jangka pendek membuang jauh-jauh asumsi bahwa persentase kursi yang akan diperoleh masing-masing orsospol sama dengan persentase suara secara nasional serta diberi penjelasan mengenai perubahan-perubahan lainnya.
Saran
Untuk pemilu yang akan diadakan dalam waktu singkat, praktek “massa mengambang” perlu dihapuskan atau sekurang-kurangnya diberlakukan terhadap semua partai. Begitu pula intervensi aparatur yang berlebih-lebihan perlu dikurangi dengan memberi kesempatan kepada pegawai negeri untuk memilih partai sesuai seleranya, dan menghapuskan “target-targetan”. Dua tindakan ini akan menjadikan pemilu yang akan datang – dengan sistem apa pun – lebih jujur dan adil.
Sebagai jalan keluar dari dilema yang menyangkut sistem pemilu dapat dipikirkan suatu sistem proporsional yang disempurnakan dengan menyediakan dua cara memilih kepada si pemilih. Mereka yang ingin suatu cara sederhana dapat mencoblos tanda gambar seperti berlaku sampai sekarang; mereka yang ingin memberi preferensi kepada orang tertentu dapat mencoblos namanya dalam daftar calon yang dicantumkan di bawah tanda gambar. Suara yang diberikan kepada orang tertentu itu otomatis diberikan kepada partainya.
Sistem ini telah dipakai 43 tahun yang lalu (1955) dengan hasil yang memuaskan. Dengan cara ini kita dapat di satu pihak mengatasi masalah renggangnya hubungan antara wakil dan constituency (kelemahan sistem proporsional), di pihak lain dapat menghindari bias terhadap partai kecil (kelemahan sistem distrik).
Analisis di atas ini dimaksud untuk pelaksanaan pemilu dalam jangka pendek. Untuk masa berikutnya, misalnya tahun 2003, jika ingin memakai sistem distrik, ada cukup waktu untuk mendiskusikan pro dan kontranya serta mensosialisasikan perubahan ini kepada masyarakat ramai. Sementara itu partai-partai baru memperoleh kesempatan luas untuk mengkonsolidasikan pendukungnya sampai dalam masyarakat.
Miriam Budiardjo, guru besar luar biasa FISIP – UI.
Sumber: KOMPAS edisi Rabu 10 Juni 1998