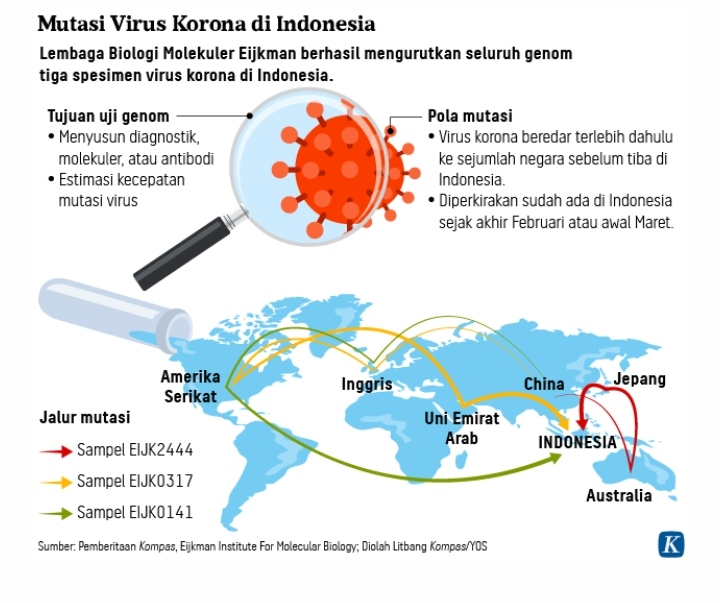Tanpa uji klinis, penderita akan menerima perawatan yang tidak efektif dan berbahaya, dokter membuang waktu untuk intervensi yang tidak berguna, dan biaya terhambur percuma.
Ketika para dokter dan peneliti berjuang untuk menyeimbangkan kekakuan protokol dengan kecepatan uji klinis, penderita terpapar Covid-19 menunggu pengobatan yang manjur. Menemukan obat Covid memang memerlukan perjalanan panjang dan mahal, dimulai dengan uji hewan coba hingga transisi uji coba ke manusia untuk keamanan dan kemanjuran.
 Hingga kini belum ada satu obat pun yang disetujui secara klinis untuk mengobati Covid-19. Akibatnya, dokter memiliki dua pilihan: menerapkan perawatan eksperimental atau tidak mengobati pasien sama sekali. Keduanya tentu saja menimbulkan dilema etik. Mungkinkah mempersingkat rentang waktu yang lama?
Hingga kini belum ada satu obat pun yang disetujui secara klinis untuk mengobati Covid-19. Akibatnya, dokter memiliki dua pilihan: menerapkan perawatan eksperimental atau tidak mengobati pasien sama sekali. Keduanya tentu saja menimbulkan dilema etik. Mungkinkah mempersingkat rentang waktu yang lama?
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pendapat klasik: penggunaan obat taraf eksperimental untuk Covid-19 tidak diizinkan regulator di mana pun. Bukti menunjukkan, sebagian besar obat tidak berfungsi seperti diharapkan ketika diuji coba.
Yang sering dilupakan adalah ”uji klinis sebenarnya melindungi pasien dari kemungkinan bahaya dari pengobatan eksperimental”. Secara etis, pandemi bukan alasan untuk melewati langkah-langkah perlindungan ini.
Pendapat pragmatis: adalah etis menggunakan obat yang telah disetujui untuk kondisi penyakit lain sebagai perawatan. Contoh, pada ebola, flu babi, zika, dan sekarang Covid-19. Juga pemanfaatan plasma konvalesen, obat virus lopinavir-ritonavir dan obat rheumatoid arthritis Actemra, yang bukan ”indikasi untuk Covid-19”.
Dokter mengamati ada semakin banyak alternatif pengobatan dan berurusan dengan tantangan/dilema etik.
Uji klinis dan pengawasan
Ketika menggunakan obat eksperimental, dokter wajib menerapkan ”metode sistematis” sebaik mungkin, yaitu bagaimana pasien ditangani dengan dosis, waktu pengobatan, dan progres penyembuhannya. Walaupun bukan penelitian, perlu pengamatan sistematis dan interpretasinya.
Misal, setelah beberapa hari/minggu, pada lebih dari 10 penderita yang diberi obat yang bukan indikasinya, ternyata tidak timbul ”risiko berbahaya dan aman”. Ini merupakan bukti subyektif yang ”terbebas” dari pelanggaran prinsip etik, yaitu ”do no harm”; dan, intervensi ini dapat dikategorikan sebagai ”uji klinis fase I”, walau belum terbukti manjur.
Banyak uji klinis Covid-19 saat ini didasarkan pada perawatan eksperimental awal tersebut. Salah satunya adalah prakarsa global pemanfaatan terapi tambahan plasma convalescene (penyembuhan) dan penelitian lopinavir-ritonavir. Keduanya walau memberi kesan bahwa obat ini tidak efektif—karena sampel penelitian ini masih kecil/terbatas—diusulkan uji klinis dengan subyek yang lebih besar sebagai pembuktian yang sahih.
Contoh lain adalah uji klinis yang sedang berlangsung dalam pengobatan radang sendi Actemra, chloroquine antimalaria, dan favipiravir obat flu Jepang.
Optimisme uji klinis pada pandemi Covid-19 meningkat berkaitan dengan ”kecepatan proses dan kemudahan” merekrut penderita sebagai subyek penelitian. Namun, yang tidak mudah adalah menentukan ”bagaimana karakteristik ideal kriteria inklusi dan eksklusi”, berikut interpretasi dari intervensi yang diberikan.
Standar emas uji klinis adalah hadirnya plasebo (tidak mengandung obat apa pun). Dalam keadaan pandemik, pemberian plasebo saja tidak dimungkinkan karena risiko akan jauh lebih besar sehingga sebagai gantinya adalah ”perawatan yang dianggap standar” (CIOMS 2016, Bab 5). Faktanya, sebagian besar obat Covid-19 belum menunjukkan kemanjuran meyakinkan atau sebaliknya malah berbahaya.
Obat lopinavir-ritonavir diujicobakan bersama pemberian oksigen, ventilasi, dan dukungan untuk memompa darah, fungsi ginjal, dan tekanan darah sesuai kebutuhan. Selanjutnya juga diajukan ”uji klinis adaptif”, yaitu menguji berbagai obat terhadap satu sama lain, atau menggabungkan untuk melihat apakah meningkatkan efektivitas.
 Pola ini memungkinkan perawatan obat tertentu ditinggalkan secara lebih cepat, jika tampak tidak efektif, dan memungkinkan lebih banyak pasien memiliki akses ke perawatan yang berpotensi efektif. Plasma konvalesen dapat diberikan dalam kerangka tiga kategori uji klinis-Investigational New Drug (IND-FDA, April 2020), yaitu clinical trial, expanded access, dan single patient emergency IND.
Pola ini memungkinkan perawatan obat tertentu ditinggalkan secara lebih cepat, jika tampak tidak efektif, dan memungkinkan lebih banyak pasien memiliki akses ke perawatan yang berpotensi efektif. Plasma konvalesen dapat diberikan dalam kerangka tiga kategori uji klinis-Investigational New Drug (IND-FDA, April 2020), yaitu clinical trial, expanded access, dan single patient emergency IND.
Terbaik adalah cara uji klinis double-blind, artinya baik dokter maupun pasien tidak tahu apakah menerima obat yang sedang diuji. Bias dapat dikesampingkan karena dokter tidak dapat secara selektif memberikan pengobatan kepada pasien yang dianggap lebih sakit.
Keadaan demikian sering ditemui saat pengobatan/intervensi non-uji klinis, yang tidak dipandu oleh protokol penelitian yang ketat. Karena itu, WHO memberi solusi: uji klinis dimungkinkan tanpa double blind, pertimbangannya adalah keseimbangan antara ketelitian dan kecepatan.
Masalah etik lebih sulit bagi uji klinis vaksin Covid. Perbedaannya, obat diberikan kepada orang yang sudah sakit; sebaliknya, vaksin diberikan kepada orang sehat.
Dalam perjalanannya, dibutuhkan sejumlah besar subyek sakit dan sehat untuk menentukan keamanan dan efektivitas di samping waktu yang lebih lama. Di masa lalu, pengembangan vaksin flu babi di AS (1976) ternyata menimbulkan 10 kasus sindrom Guillain-Barre per 1 juta orang yang mendapat vaksinasi. Meskipun sebagian besar pulih, 25 orang meninggal karena vaksin.
Pilihan akses
Ketika dokter dan peneliti berjuang untuk menyeimbangkan kekakuan protokol dengan kecepatan uji klinis, pasien Covid-19 berharap tidak menunggu lama dan mendapat pengobatan yang manjur.
Di AS, contoh uji coba klinis Covid yang dapat dijadikan acuan adalah pemberian obat remdesivir; obat ini tidak disetujui diberikan untuk mengobati kondisi sakit apa pun, artinya pasien hanya dapat mengakses obat jika mereka diterima dalam uji klinis. Dalam analisis secara statistik, sebagian besar obat tidak ditemukan efektif, dan bahkan berfungsi tidak sebagaimana mestinya.
Ketentuan baku adalah jika tidak melakukan uji klinis terkontrol dengan hati-hati, dengan plasebo, upaya ini mengecewakan dan membuang waktu.
Mayoritas berpendapat bahwa untuk menerapkan standar terapi yang tepat, uji coba memang memakan waktu lebih lama, dengan subyek lebih besar; karena sulitnya memastikan apakah obat tersebut berdampak positif.
Yang perlu diingat adalah adanya anggapan bahwa uji klinis merupakan batu penghalang. Padahal, faktanya, mayoritas dari obat-obatan yang dipakai untuk Covid tidak melalui pengujian sistematis, dan gagal dalam uji klinis yang ketat.
Sebaliknya, meskipun bekerja dengan kecepatan sangat tinggi, prosedur uji klinis baku mutlak diperlukan.
Tanpa uji klinis, penderita akan menerima perawatan yang tidak efektif dan berbahaya, dokter membuang waktu untuk intervensi yang tidak berguna, dan biaya terhambur percuma.
(Triono Soendoro Ketua Komisi Nasional Etik Penelitian Kesehatan 2016-2019; Ketua Asosiasi Komite Etik Penelitian Indonesia (Akepin))
Sumber: Kompas, 11 Mei 2020