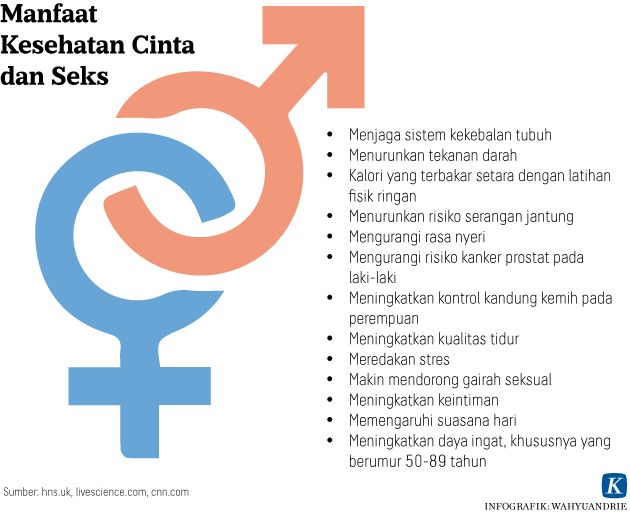Manusia adalah makhluk seksual, punya dorongan seksual, butuh berhubungan seks dan ingin kepuasan seksual. Namun, bagi sebagian orang, seks bukan lagi jadi hal yang menyenangkan. Terus turunnya gairah seksual masyarakat itu dianggap sebagai puncak ketidakbahagiaan manusia modern.
Di Indonesia, isu menurunnya frekuensi hubungan seksual masyarakat memang belum jadi perhatian. Wajar, hingga kini Indonesia masih berusaha menurunkan fertilitas warganya hingga mencapai titik penduduk tumbuh seimbang.
Namun, dugaan turunnya hasrat seksual itu sudah muncul dari analisis terhadap data hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2017 yang dipublikasikan 9 Oktober 2018. Meski tingkat pemakaian kontrasepsi modern turun dan jumlah anak ideal versi laki-laki naik, tingkat fertilitas masyarakat justru turun.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Walau belum ada data tentang turunnya frekuensi hubungan seksual di Indonesia, apa yang dialami Daya (39) bisa jadi pertanda. Perempuan yang tinggal di Bogor itu selalu kelelahan saat pulang bekerja dari kantornya di Jakarta. Hanya untuk kerja 8 jam sehari, ia harus menempuh perjalanan 5 jam pergi-pulang dengan sepeda motor dan kereta.
Tiap hari, ia keluar rumah pagi buta dan tiba di rumah saat hari gelap. Di rumah pun, ia masih disibukkan berbagai urusan, seperti membersihkan rumah, memasak, dan membantu anak mengerjakan pekerjaan rumah. Kesibukan dan kelelahan itu membuat pikiran dan hasratnya berhubungan suami-istri tergerus.
Hal serupa dialami Vetty (40), warga Bandung, Jawa Barat. Perempuan yang masih punya anak balita itu mengaku keinginan untuk berhubungan suami-istri mencapai titik nadir setelah melahirkan hingga anaknya berumur 1,5 tahun. Mengurus anak, rumah dan pekerjaan paruh waktu menguras tenaganya.
Saat anak-anak makin besar, gairah itu tumbuh kembali. Namun karena suaminya bekerja di luar kota, praktis dia hanya bisa melakukannya saat akhir pekan saja. “Sebulan paling hanya 4-6 kali saja,” katanya.
Masalah Daya dan Vetty itu bisa jadi cerminan perilaku seksual kaum urban Indonesia. Beban kerja dan pekerjaan domestik, stres perjalanan, hingga terpisahnya tempat tinggal suami-istri berpotensi menurunkan frekuensi dan kualitas hubungan seksual mereka.
Bisa saja kita menyangkal tak memiliki masalah seperti yang dihadapi Daya dan Vetty. Namun jika hal terakhir dan pertama yang kita lihat sebelum dan sesudah tidur bukanlah suami atau istri kita, kita sebenarnya tahu, seberapa sering dan berkualitas hubungan seksual kita.
Negara maju
Persoalan turunnya frekuensi hubungan seksual itu jadi perhatian serius di sejumlah negara maju. Kurangnya frekuensi hubungan suami-istri berkorelasi dengan rendahnya tingkat kesuburan masyarakat, situasi yang membuat negara-negara maju kekurangan tenaga kerja produktif dan menghadapi lonjakan penduduk lansia.
 Studi Jean M Twenge dkk (2017) menyebut frekuensi orang Amerika Serikat berhubungan seks turun 15 persen antara 1990an hingga 2010an. Sebelumnya, mereka berhubungan seks 5,2 kali sebulan, tapi dua dekade berikutnya jadi 4,4 kali sebulan.
Studi Jean M Twenge dkk (2017) menyebut frekuensi orang Amerika Serikat berhubungan seks turun 15 persen antara 1990an hingga 2010an. Sebelumnya, mereka berhubungan seks 5,2 kali sebulan, tapi dua dekade berikutnya jadi 4,4 kali sebulan.
Di Inggris, Survei Perilaku Seksual dan Gaya Hidup Nasional (Natsal) 2013 menemukan masyarakat berhubungan seks 6,3 kali sebulan pada 2000 dan jadi 5 kali sebulan pada 2013. Situasi serupa terjadi di Australia, yaitu dari 7,2 kali sebulan pada 2004 jadi 5,6 kali sebulan pada 2014.
Kondisi di Jepang mungkin yang paling mengkhawatirkan. Survei Perkumpulan Keluarga Berencana Jepang (JFPA), dikutip dari nippon.com, 23 Februari 2017, menyebut 47,2 persen pasangan menikah di Jepang tidak melakukan hubungan seks sama sekali minimal satu bulan. Jumlah itu lebih tinggi 15,3 poin dari survei serupa pada 2004.
Kekurangtertarikan warga Jepang terhadap seks itu sudah terjadi sejak muda. Survei Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Jepang tentang hubungan laki-laki dan perempuan yang dikutip dari japantimes.co.jp, 29 April 2012, menunjukkan terus naiknya pemuda laki-laki dan perempuan yang tak tertarik dengan seks.
Pada 2008, 11,8 persen laki-laki dan 25 persen perempuan Jepang umur 20-24 tahun tidak berminat dengan seks. Pada 2010, jumlahnya naik jadi 21,5 persen pada laki-laki dan 35 persen pada perempuan. Di usia yang lebih muda, makin besar keengganannya terhadap seks.
Turunnya hasrat seksual pada anak muda itu terjadi di banyak negara. Studi Twenge dkk (2015) menunjukkan, pada usia yang sama, generasi milenial (generasi Y, lahir 1980-2000) paling sedikit berhubungan seks dibanding generasi X (lahir 1960-1980) dan generasi baby boomer (lahir 1940-1960).
Namun, Guru Besar Andrologi dan Seksologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Denpasar Wimpie Pangkahila menegaskan tidak ada ketentuan berapa kali hubungan suami-istri harusnya dilakukan dalam seminggu. Namun jika kurang, tentu menimbulkan ketidakpuasan.
“Hubungan seks yang sehat dilakukan karena kesepakatan kedua pihak, terserah berapa kali, namun harus bisa memuaskan keduanya,” tambahnya.
Kesenangan
Antropolog jender, seksualitas, dan kesehatan di Departemen Antropologi Universitas Indonesia, Irwan Martua Hidayana mengatakan fungsi dasar seks adalah untuk kesenangan. Namun di masa lalu, fungsi reproduksi seks tak bisa dilepaskan. Hal itu setidaknya terlihat dari berbagai naskah kuno atau relief candi terkait seksualitas yang ada di sejumlah negara.
Setelah revolusi industri, fungsi kesenangan dan reproduksi seks dipisahkan. Berkembangnya teknologi kontrasepsi membuat orang makin tidak khawatir, hubungan seks bisa memicu kehamilan. Saat inilah, seks lebih dimaknai sebagai rekreasi.
Selain itu, masyarakat modern mencoba memandang seks sebagai sains hingga memunculkan berbagai pengetahuan guna mewujudkan seks ‘berkualitas’. Akibatnya, hubungan suami-istri jadi hal yang terukur yang justru menimbulkan tekanan dan stres hingga hasrat seksual pun turun. “Seks jadi hal teknis belaka dan lupa kesenangannya,” katanya.
Namun, penyebab utama dari turunnya hasrat seks diyakini karena manusia modern memiliki beban jiwa yang lebih besar dibanding generasi sebelumnya. Beban jiwa itulah yang akhirnya memengaruhi gairah dan kepuasan seksual mereka.
Teknologi, khususnya internet, juga sering dituding menurunkan aktivitas seks masyarakat. Pornografi dan media sosial dinilai bisa mengalihkan perhatian, kesenangan, dan keinginan untuk menikah dan berhubungan seks. Namun, dampak itu masih diperdebatkan karena studi lain justru menunjukkan pornografi terukur, bukan kecanduan, bisa membangkitkan gairah seksual.
 Selain teknologi, beban hidup juga dianggap menyebabkan turunnya gairah seksual. Beban pekerjaan, tekanan kehidupan, mobilitas yang tinggi, stres dan kelelahan fisik bisa memengaruhi hasrat seks. Demikian pula dengan situasi krisis politik, ekonomi, dan sosial budaya.
Selain teknologi, beban hidup juga dianggap menyebabkan turunnya gairah seksual. Beban pekerjaan, tekanan kehidupan, mobilitas yang tinggi, stres dan kelelahan fisik bisa memengaruhi hasrat seks. Demikian pula dengan situasi krisis politik, ekonomi, dan sosial budaya.
Namun alasan kelelahan tak selamanya valid. Studi JS Hyde dkk (1998) menunjukkan aktivitas, kepuasan dan keinginan seksual antara ibu rumah tangga dan ibu yang bekerja tidak berbeda. Bahkan, studi Twenge dkk (2015) menunjukkan beban kerja yang tinggi justru meningkatkan frekuensi hubungan seks.
Meski demikian, pekerjaan yang buruk, memberi banyak tekanan atau memicu stres bisa memperburuk kesehatan mental seseorang dibanding yang menganggur. Studi Evan Atlantis dkk (2012) menunjukkan depresi mengurangi hasrat seksual dan menambah risiko disfungsi seksual. Stres mengubah produksi hormon hingga membentuk citra negatif pada tubuh dan pasangan.
Situasi itu bisa menjelaskan mengapa gairah seks generasi milenial lebih rendah dibanding generasi sebelumnya walau mereka lebih terbuka terhadap seks. Anak milenial lebih rentan stres. Mereka memiliki kekhawatiran lebih besar terkait pekerjaan, perumahan, dampak perubahan iklim, hingga rusaknya ruang komunal dan kehidupan sosial.
Karena itu, turunnya frekuensi hubungan seks diyakini jadi cerminan kesehatan mental masyarakat. Tak berlebihan jika kurangnya gairah seks dipandang sebagai puncak beban mental manusia modern.
Situasi itu dikhawatirkan akan menjadikan masyarakat murung, menurunkan produktivitasnya dan meningkatkan beban kesehatan. Ujungnya, kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat akan turun, suatu hal yang jadi fokus tujuan pembangunan.
Bahkan, kekhawatiran punahnya bangsa bisa terjadi karena rendahnya frekuensi hubungan seks bisa membuat tingkat fertilitas terlalu rendah. Karena itu, jika Indonesia ingin menjaga pertumbuhan penduduk seimbang mulai 2020, masalah turunnya gairah seks tidak bisa disepelekan, khususnya di daerah dengan tingkat fertilitasnya kurang dari 2,1 anak per perempuan.
Oleh M ZAID WAHYUDI
Sumber: Kompas, 4 November 2018