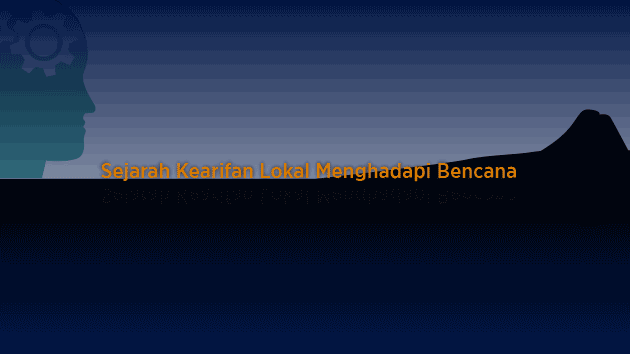Korban Jiwa Terus Berjatuhan
Tingginya korban jiwa dan kerugian materi akibat berbagai jenis bencana alam menunjukkan lemahnya aspek pencegahan dan pengurangan risiko dalam pembangunan di Indonesia. Karena itu, perlu perubahan perspektif dan penanganan bencana yang selama ini fokus pada respons setelah kejadian ke pengurangan risiko.
Jatuhnya sembilan korban tewas akibat awan panas Gunung Sinabung, Mei lalu, dan rusaknya 1.955 rumah warga akibat gempa berkekuatan kecil di Sumatera Barat, 2 Juni silam, menambah panjang daftar korban jiwa dan kerugian materi akibat bencana. Padahal, korban jiwa dan kerugian itu bisa dikurangi jika penanganan bencana fokus pada mitigasi.
Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), awal Januari hingga 6 Juni 2016, bencana alam menewaskan 154 orang, menyebabkan 1,6 juta jiwa terdampak dan mengungsi. Bencana juga menyebabkan 14.500 rumah dan 462 unit fasilitas umum rusak. Kerugian akibat bencana berkisar Rp 50 triliun-Rp 100 triliun per tahun.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Namun, tahun lalu, kerugian akibat bencana kebakaran hutan saja Rp 221 triliun,” kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho di Jakarta, Senin (13/6).
Menurut peneliti kebencanaan dari Pusat Penelitian Geoteknologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Eko Yulianto, tingginya korban jiwa dan kerugian materi akibat bencana disebabkan pengurangan risiko belum menjadi arus utama pembangunan.
Deputi Geofisika Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Masturyono mengakui, pengurangan risiko bencana belum menjadi arus utama pembangunan. “Dalam penganggaran, misalnya, bencana tidak masuk prioritas nasional meskipun masuk RPJM (rencana pembangunan jangka menengah),” ucapnya.
Peneliti gempa dan tsunami Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Widjo Kongko, menambahkan, tak adanya pengarusutamaan bencana dalam pembangunan tampak di sejumlah proyek strategis nasional yang tidak serius dilandasi aspek mitigasi. Misalnya, pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung dan rencana pembangunan bandar udara di zona rentan tsunami di Kulon Progo, Yogyakarta.
“Meski Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 mendorong pergeseran paradigma penanganan bencana dari responsif ke pencegahan, faktanya penanggulangan bencana fokus ke tindakan respons bencana,” kata Eko.
Kegiatan yang difokuskan pada pengurangan risiko atau pencegahan amat minim. Akibatnya, kapasitas warga dan pemerintah, khususnya di daerah, dalam menekan risiko bencana terbatas.
Kegagalan itu disebabkan penanggulangan bencana oleh BNPB cenderung jalan sendiri. “Seharusnya kita meniru strategi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam mengarusutamakan isu jender. Jadi, soal bencana seharusnya tak hanya ditangani BNPB, tetapi menjadi arus utama setiap lembaga atau kementerian,” ujarnya.
Anggaran terbatas
Sutopo menyoroti soal utama penanggulangan bencana di Indonesia, antara lain dana terbatas. Anggaran BNPB tahun 2016 sekitar Rp 1,1 triliun, yakni Rp 807,8 miliar bagi program penanggulangan bencana dan Rp 292,2 miliar untuk dukungan manajemen sarana prasarana, pengawasan, dan peningkatan akuntabilitas aparatur.
 Adapun dana cadangan penanganan bencana di Kementerian Keuangan Rp 4 triliun, yakni Rp 2,5 triliun bagi penanganan darurat dan Rp 1,5 triliun untuk rehabilitasi dan rekonstruksi. “Dana terlalu kecil dibandingkan kebutuhan, apalagi ancaman bencana meningkat,” kata Sutopo.
Adapun dana cadangan penanganan bencana di Kementerian Keuangan Rp 4 triliun, yakni Rp 2,5 triliun bagi penanganan darurat dan Rp 1,5 triliun untuk rehabilitasi dan rekonstruksi. “Dana terlalu kecil dibandingkan kebutuhan, apalagi ancaman bencana meningkat,” kata Sutopo.
Idealnya, BNPB mendapat dana Rp 10 triliun-Rp 15 triliun per tahun bagi penanganan bencana. “Bappenas pernah menginisiasi, penanggulangan bencana perlu minimal 1 persen APBN. Bandingkan dengan Jepang yang mengalokasikan dana penanganan bencana minimal 6 persen APBN per tahun,” ujarnya.
Dana penanganan bencana di daerah pun terbatas. Di Lampung, misalnya, dana pemda hanya cukup untuk biaya operasional, evakuasi korban, dan logistik saat bencana. Akibatnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah sulit mengadakan simulasi bencana bagi petugas.
Namun, menurut Eko, soal pengelolaan kebencanaan di Indonesia lebih pada salah perspektif. “Bencana lebih dipandang sebagai soal teknis semata sehingga fokus kegiatan mitigasi bencana lebih pada penyediaan infrastruktur fisik, bukan pada warganya,” ucapnya.
Perubahan perilaku
Menurut Eko, tujuan pembangunan yang utama ialah pembangunan manusia. Perspektif ini mesti jadi landasan menekan risiko bencana. “Jadi pengelola pengurangan risiko bencana (khususnya BNPB dan BPBD), harus melihat perilaku manusia jadi pemicu utama bencana,” ucapnya.
Terkait hal itu, pengurangan risiko bencana seharusnya fokus pada perbaikan perilaku warga bermuara terkait pengurangan nilai kerentanan sosial, fisik, dan ekonomi warga. “Jadi, penanggung jawab utama pengurangan risiko bencana seharusnya di Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,” kata Eko.
Persoalan kapasitas manusia itu tampak pada kasus jatuhnya kembali korban jiwa akibat terjangan awan panas di Gunung Sinabung, Kabupaten Karo. Pemerintah menetapkan zona bahaya yang tak boleh dimasuki, tetapi diabaikan warga.
Ahli gunung api yang juga mantan Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Surono menyoroti kelemahan manajemen bencana. “Ini mencerminkan manajemen bencana lemah. Kalau PVMBG merekomendasikan relokasi, seharusnya cepat direlokasi. Pemerintah harus hadir,” ujarnya.
Proses relokasi pengungsi berlarut-larut menyebabkan warga kembali ke ladang. Sejumlah pengungsi Sinabung mengeluhkan lambannya proses relokasi.(AIK/WSI/VIO)
—————
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 14 Juni 2016, di halaman 1 dengan judul “Risiko Bencana Diabaikan”.