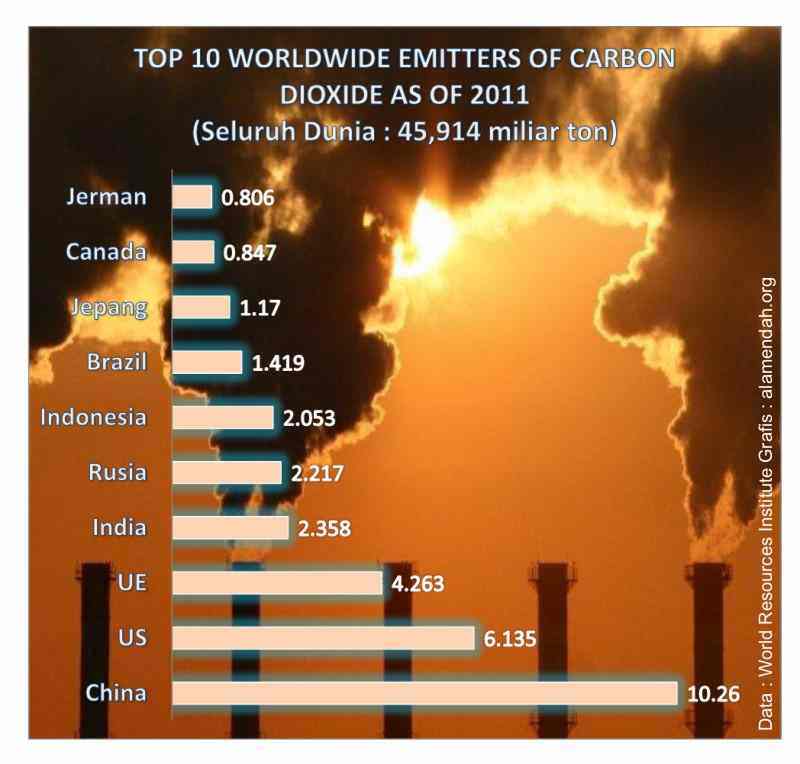Empat puluh lima tahun lalu, tanggal 22 April 1970, sekitar 20 juta warga negara Amerika Serikat tercerahkan: betapa pentingnya manusia melindungi sumber daya alam. Laut, atmosfer, daratan, dan (kondisi) biologi, perlu dilindungi untuk (diwariskan pada) generasi mendatang.
Ketika itu elang gundul (Bald eagle) lambang AS terancam punah, paus di bumi juga mengalami nasib sama. Kasus domestik, Sungai Cuyahoga polusinya sedemikian parah dan sungai itu terbakar. Maka, lahirlah Hari Bumi dengan tokohnya Gaylord Nelson-mantan Gubernur Wisconsin, AS, yang saat itu duduk di kursi Senat AS. Hari ini, di seluruh penjuru dunia, sebagian warga merayakan Hari Bumi.
Kata konsumsi dan keserakahan belum memasuki kesadaran para aktivis pencetus Hari Bumi 45 tahun lalu. Kalimat terkenal Mahatma Gandhi,
”Dunia bisa memenuhi kebutuhan setiap orang, namun tak cukup untuk memenuhi keserakahan setiap orang” seakan tidak menemukan konteksnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Seiring dengan revolusi industri pada 1850-an, produksi pun bertambah diiringi peningkatan konsumsi. Pertumbuhan ekonomi dibaca secara keliru sebagai salah satu indikator kesejahteraan. Ironisnya, pertumbuhan ekonomi justru makin mengonsentrasikan kapital pada sebagian kecil komunitas.
Manusia sebagai ”spesies kera dengan imajinasi tinggi” telah termakan oleh pengetahuan dan inovasi yang diciptakannya sendiri sebagai hasil dari imajinasi intelektual mereka. Revolusi industri dengan cepat mendorong tumbuhnya kebutuhan.
Filosof Ivan Illich seperti dikutip Alan Durning dalam ”How Much Is Enough?” (Worldwatch Institute, 1992) menyatakan, apa yang didengar orang Amerika pada 1970-an sudah berbeda dengan apa yang mereka dengar di tahun 1920-an. Kata yang diucapkan tahun 1920-an ditujukan kepada dia sebagai individual atau seseorang. Tahun 1970-an, kata-kata itu ditujukan kepada kita sebagai bagian dari pasar yang bersifat massal.
Teks yang kita baca, gambar yang kita lihat, tempat-tempat yang kita kunjungi, semuanya memanjakan indera kita, memicu rasa nikmat.
Konsumerisme tumbuh pesat. Manusia terlena. Mereka tak hirau bahwa bumi terbatas. Bahwa sumber daya terbatas. Mampukah bumi yang terbatas memenuhi nafsu konsumerisme yang tanpa batas? Tepat seperti apa yang diucapkan Mahatma Gandhi.
Industri yang ditopang energi fosil dengan sigap memproduksi barang-barang konsumsi, mengakibatkan ”selimut hangat” atmosfer meningkat suhunya akibat kenaikan konsentrasi gas rumah kaca (GRK)
sebagai dampak konsumsi bahan bakar fosil. Awal tahun ini konsentrasi gas CO2 di atmosfer melampaui batas 400 bagian per sejuta (ppm). Batas 400 ppm adalah batas titik balik. Maka, tak lagi dimungkinkan terjadi titik balik.
Konferensi Perubahan Iklim Pertemuan Para Pihak ke-21 di Paris adalah momentum lahirnya peradaban baru dunia. Ilmuwan yang jadi utusan khusus perubahan iklim Inggris, Sir David King, membandingkannya dengan kondisi pasca Perang Dunia II, tahun 1945. Hancurnya kemanusiaan dalam perang dunia telah melahirkan kesadaran manusia untuk eksis. Lahirlah Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Menurut King, konferensi di Paris terjadi pada situasi yang mirip dengan situasi tahun 1945. Manusia terancam eksistensinya. Dengan laju emisi GRK seperti sekarang, jika berlanjut, pada tahun 2100 suhu bumi bisa meningkat sekitar lima derajat dibandingkan suhu seratus tahun lalu, atau sekitar empat derajat celsius dari suhu sekarang. Bencana banjir, badai, iklim, dan cuaca ekstrem akan terjadi lebih sering dan lebih masif. Kerusakannya pun masif.
Pertanyaan eksistensial yang muncul hanya bisa dijawab dengan peradaban baru yang berpeluang lahir di Paris jika negara-negara sepakat menurunkan emisi GRK. Inovasi teknologi lalu jadi keniscayaan. Lantas, konsumerisme…? —– BRIGITTA ISWORO LAKSMI
———————-
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 22 April 2015, di halaman 14 dengan judul “Peradaban Baru”.